-
Novel Ghost of The River Musi
I dedicated this story for my last parents, my sweet baby ‘Rudysta Dihyah Al-Kalabi’, my brother & sister, my friends and my inspirations (musi river & hellowen ‘forever and one’)
Sinopsis25 tahun lalu, Dhea pernah di selamatkan Antu Banyu saat tenggelam di sungai Musi Mahluk mengerikan yang konon gemar menghisap darah dan otak manusia. Dia merasa yakin, mahluk itu memperingatkannya untuk tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapa pun kalau tidak ingin terjadi bencana. Hal tersebut juga Dhea sampaikan kepada teman-teman yang berenang dengannya dan sempat menyaksikan mahluk air itu. Tetapi sayangnya, teman-temannya tidak mengindahkan peringatan itu. Akibatnya, terjadi hal-hal menakutkan bagi mereka. Jamie tiba-tiba meninggal dunia. Hany yang mendengar kisah tentang Antu Banyu itu dari Jamie, juga tewas dalam kecelakaan. Sementara Vina, tewas terbakar di karaoke tempatnya bekerja menjelang hari pernikahannya. Budi tewas dalam kecelakaan di jalan raya, Doddy menjadi terganggu jiwanya. Dan Eve, satu-satunya yang tidak melihat Antu Banyu itu tetapi menceritakan kisah tersebut kepada kakaknya. Malah membuat kakaknya pun kehilangan ingatannya. Dhea pun merasa bersalah ketika kakak perempuannya kemudian juga mengalami gangguan jiwa, setelah secara kebetulan membaca diary Dhea yang telah menuliskan kenangan tentang peristiwa di sungai Musi itu. Bukan itu saja. Kecelakaan yang dialami ayah Dhea saat membangun rumah pun disadari kemudian ada kaitannya dengan pengungkapan peristiwa pertemuannya dengan Antu Banyu. Dan ternyata, masih banyak korban-korban lain yang akan berjatuhan karena mengetahui tentang peristiwa itu. Mungkin, salah satunya, termasuk kamu….Aku menggeleng,”Tidak, rasanya aku baik-baik saja” (special to my baby Rudysta Dihyah Al-Kalabi)
Ghost of The River (the true story of Sri Widya)Plaju, 1983
Pagi itu kami memutuskan untuk meneruskan kegiatan bermain di sungai. Setelah kegiatan bermain di sekitar rumah sudah tidak begitu menyenangkan lagi. Bosan rasanya jika pagi-pagi kami main kawin-kawinan lagi. Mengarak si Eve dengan si Doddy yang duduk diatas sepeda roda tiga warna hijau tua. Dimana kami kemudian sibuk mendorong sambil berlari sekencang-kencangnya. Jenuh rasanya melihat muka si Eve tebal dengan make-up seperti biduan dangdut yang mau pentas. Bosan juga mengawasi kegiatan para penyapu dan penyabit rumput di lapangan bola Patra Jaya milik Pertamina. Atau berkumpul di pekarangan atau belakang rumah salah satu diantara kami, sambil main rumah-rumahan.Demikianlah kegiatan kami, anak-anak penghuni asrama tentara di kawasan Plaju itu. Atau yang biasa disebut anak kolong. Setelah ayah-ayah kami setiap pagi itu pergi dengan seragam lengkap menaiki truk hijau besar, dimana kami kemudian akan berlari mengejar dan terus melambai sampai gerbang pengawalan (gerbang masuk asrama yang dijaga beberapa tentara bersenjata), barulah kegiatan kami dimulai. Kami memang merupakan para anak tentara yang masih kecil-kecil. Belum kenal Taman Kanak-Kanak, atau karena alasan tertentu tidak dimasukkan ke sekolah itu. Seperti aku, yang meski hampir lima tahun tapi tidak juga mengenal TK. Meski ada TK di lingkungan asrama itu. Karena ayahku yang agak kolot dan super hemat itu lebih setuju jika aku nantinya langsung masuk SD saja.“TK itu cuma tempat main-main saja. Kau bawa duit dan makanan dari rumahmu sebakul, lalu kau makan dengan teman-temanmu disana. Menghabis-habiskan uang saja. Ah, sudahlah. Jika kau ingin belajar maka belajarlah di rumah. Kau akan jauh lebih pintar dari teman-temanmu yang berkumpul di TK itu” demikian nasehat ayahku, jika aku merengek minta sekolah di TK seperti teman-teman seusiaku.
Dari keempat saudaraku, hanya kakak perempuanku yang sempat mengecap indahnya bersekolah di TK. Suatu hal yang menurut orangtuaku sama sekali tidak ada faedahnya. Kedua kakak laki-lakiku mengaku justru lebih senang tidak sempat berkenalan dengan tempat yang menurut mereka kurang maskulin itu. Dan aku, si bungsu ini, akhirnya hampir setiap pagi hanya mampu menatap dengan penuh kecemburuan terhadap teman-teman yang berseragam putih dan hijau itu. Mereka berbedak putih tebal, membawa ransel berisi dua tangkup roti dan sebotol air minum. Terkadang ditangan mereka juga melambai lembaran uang seratus perak sebagai bekal buat jajan.
Sumpah mati, aku sangat membenci pemandangan ini. Sebenci aku menahan kejengkelan akibat kekerasan pola pikir orangtuaku yang seakan mentabukan anaknya untuk mengenal yang namanya sekolah TK itu. Mereka tidak tahu bagaimana perasaanku. Betapa tertekannya aku melihat mereka bersekolah di pagi hari yang ceria. Orangtuaku seperti tidak merasakan betapa aku terluka jika beberapa diantara mereka menertawakan aku yang sudah terlalu tua tapi tidak juga bersekolah. Dan mungkin, karena aku sudah terlalu sering merengek bahkan sampai menangis segala, akhirnya orangtuaku dan saudaraku sedikit bersimpati juga.
Jika aku sakit, maka aku digendong ibuku untuk dibawa melihat-lihat kegiatan di TK. Suatu kenangan yang sulit kulupakan, saat ibu memelukku dengan hangat sambil mengajakku menyanyi menirukan murid-murid yang sedang latihan paduan suara. Kakak-kakakku juga sering mengajakku main di TK. Jika kegiatan di TK sudah tidak ada lagi, kami sering main ayunan, perosotan (meluncur dari kayu licin dan melingkar seperti ular) atau sekedar kejar-kejaran disana. Terkadang teman-teman yang lain pun ikut serta. Ibu juga terkadang pagi-pagi sudah mendandaniku dengan rapi. Lalu ayah menggandengku sampai ke dekat TK, lalu kami kembali lagi ke rumah. Aku tahu itu dilakukan mereka agar aku berhenti merengek-rengek jadi murid TK. Dan akhirnya aku memang berhenti merengek lagi. Bukan karena puas telah diberikan simpati, tetapi karena sudah capek dan malu sendiri.Malu jika kegiatanku setiap pagi itu dipertanyakan dan dikasihani para tetangga. Sedih karena mereka menyalahkan program hidup hemat yang dijalankan ayah dan ibu tercinta. Meski suatu hari aku memaklumi, bahwa tindakan tersebut karena ayah hanya seorang tentara berpangkat rendah dengan gaji yang tidak seberapa tetapi harus menghidupi istri serta ke-empat anaknya. Belum lagi ditambah ibunya (nenek kami) yang sudah tua. Sementara disetiap saat pintu rumah kami juga selalu terbuka demi segala saudara sepupu ayah dari antah berantah, yang selalu datang memohon bantuan seperti rumah kami itu Departemen Sosial saja.
Dan setiap pagi hariku di usia menjelang lima tahun itu akhirnya harus kuhabiskan bersama teman-teman balitaku yang memang belum waktunya mengenal TK. Jika dengan anak yang lebih besar, kami bermain karena mereka sekolah siang. Dan jika aku bermain dengan anak seusiaku, itu artinya mereka senasib karena kami kebetulan berasal dari keluarga yang sedang melancarkan program hidup hemat, cermat dan bersahaja.Pola permainan anak-anak seusia kami tentu dapat di tebak. Kalau tidak meniru kegiatan orang dewasa (seperti kawinan-kawinan itu), maka kami mencari kesenangan pribadi yang begitu rahasia. Bukan suatu hal yang aneh lagi, jika ketahuan main di sungai maka kami akan ditarik-tarik para orangtua untuk pulang ke rumah. Masih untung kalau cuma diomeli atau dijewer. Biasanya akan diterapkan sanksi khusus untuk tidak boleh keluar rumah sampai beberapa waktu lamanya.Tempat-tempat rahasia yang kami miliki, seperti hutan belukar di belakang asrama dan Sungai Musi. Jika hutan belukar yang menyeramkan itu sering jadi arena permainan anak-anak laki-laki yang sudah besar, maka sungai adalah rahasia terbesar kami. Kami yang kecil ini tidak pernah diajak anak-anak yang lebih besar untuk mencari biji keluwe (semacam buah mirip sukun yang bijinya enak direbus) atau pisang liar, karena dianggap terlalu polos dan merepotkan. Meski mereka juga kerap mandi di sungai, tetapi karena sudah besar tentu tidak ada larangan yang sifatnya keras. Larangan akan muncul jika tiba-tiba ada seorang anak tenggelam di sungai yang konon katanya dilahap Antu Banyu. Monster menakutkan yang wujudnya sendiri tidak ada yang secara jelas bisa mendiskripsikan. Belum lagi para buaya sungai yang lapar dan konon tidak kalah buasnya dengan si Antu Banyu itu. Pokoknya judulnya, serem aja.
Tetapi bagi kami, para mahluk kecil ini, bukan hanya Antu Banyu yang ditakutkan akan menyerang. Postur tubuh yang mini tentu dikhawatirkan belum dapat menjaga diri sendiri dari bahaya apa pun yang akan menyerang. Termasuk ombak besar yang menerjang akibat pengaruh kapal besar yang berlalu lalang. Dan dipastikan kami memang belum pandai berenang.
Apalagi sungai Musi bukan sungai biasa. Meski nampak terlihat tenang, arus sungai Musi tidak dapat dikatakan setenang permukaannya. Konon kondisi sungai ini mengerucut, dimana pada bagian tengah yang sempit dan sangat dalam itu (konon juga) terdapat pusaran air yang dapat menyedot apa saja. Sebagian orang percaya bahwa di bagian lengkung sungai inilah terhadap kerajaan siluman, setan atau sejenisnya. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Antu Banyu. Antu berasal dari kata hantu, dan banyu berasal dari kata air. Mahluk antah berantah yang konon hidupnya sudah ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Sebab banyak yang meyakini jika mahluk ini sebenarnya hanya hewan purba yang sanggup hidup di air maupun di darat. Mereka diyakini sebelumnya berjumlah banyak, namun karena habitatnya terdesak oleh kehidupan manusia membuat populasinya menjadi kian langka. Bahkan diyakini berevolusi sehingga bentuknya mengecil menjadi seukuran tubuh kucing. Padahal sebelumnya, ada banyak cerita dari masyarakat lama yang meyakini jika wujud mahluk yang satu ini besar luar biasa.Tapi konon, mahluk itu wujudnya saat ini mirip seekor monyet tetapi bertubuh tidak lebih besar dari kucing. Berambut panjang, bersisik dan berlendir. Suatu deskripsi yang cukup aneh bagi seekor mahluk air. Wujud ini, antara lain ku ketahui dari ibuku sendiri. Menurut ibu, saat ibu melahirkan anak pertamanya yakni kakakku, ayahlah yang mencucikan kain penuh darah yang digunakan waktu persalinan. Saat itu ayah mencuci kain-kain tersebut di Sungai Musi menjelang tengah malam. Ketika sibuk mencuci, tiba-tiba ayah melihat sesuatu yang timbul tenggelam di atas permukaan sungai. Mukanya seperti monyet. Tetapi karena ayah meyakini tidak mungkin ada monyet yang jago berenang, maka ayah langsung melempari mahluk itu dengan batu. Ayah yakin itu mahluk air yang sering disebut masyarakat dengan Antu Banyu yang terpancing bau darah dari kain yang dicuci ayah.Dan Sungai Musi yang sepanjang aliran sungainya padat dengan sejarah itu memang terus menenggelam misteri tentang Antu Banyu. Sungai ini pun wujudnya seperti laut saja. Banyak kapal besar dari negara asing seperti tidak henti-henti melintasinya. Meski kalah panjang dengan Sungai Kapuas, tapi aku yakin sungai ini mungkin lebih lebar dari sungai lainnya di nusantara. Kalau main di sungai ini, aku senang berdiri diatas batu karang. Sebenarnya itu batu besar yang dibuat untuk menghalang hantaman air sungai. Panjangnya sekitar seratus meter dengan ketinggian sepuluh meter. Konon di bangun sejak zaman penjajahan Jepang.Di seberang sana, kita masih dapat melihat Pabrik Pupuk Sriwijaya (PUSRI). Di sebelahnya juga ada Pulau Kemaro, sebuah pulau kecil yang menyajikan cerita legenda cinta Putri Fatimah dari Kesultanan Palembang dengan Pangeran Tan Bun An dari Kerajaan Tiongkok. Mereka konon mati karena menceburkan diri di sungai, karena mencari guci-guci berisi sawi busuk yang terlanjur mereka buang. Padahal guci-guci dari Tiongkok itu sebenarnya berisi emas dan permata. Orang tua Tan Bun An sengaja menutupi harta benda itu dengan sawi busuk atau biasa juga disebut sekarang sayur sawi yang diasinkan, untuk mengelabui para perompak. Tapi karena Tan Bun An mengira orang tuanya sengaja menghinanya dengan memberi barang yang tak berharga, maka dia membuangnya begitu saja.Sayangnya, guci terakhir keburu pecah sebelum terlempar ke sungai. Dan terlihatlah, tumpukan emas permata dibawah tumpukan sawi busuk. Berharap dapat menemukan guci-gucinya kembali, pangeran Tiongkok ini pun menceburkan diri ke sungai Musi. Karena tak kunjung kembali, para pengikutnya, termasuk Putri Fatimah pun ikut menceburkan diri. Konon, mereka tak pernah muncul ke permukaan lagi. Tetapi tepat di lokasi mereka menceburkan diri malah muncul pulau kecil. Pulau itu sampai kini masih sering dikunjungi warga keturunan terutama saat Imlek. Mungkin selain berziarah, mereka juga dapat menuai hikmah. Minimal menghayati kata pepatah; hormatilah segala pemberian orangtua. Atau mungkin, don’t judge book with this cover?Dan memang, masih banyak lagi kelebihan sungai Musi. Seperti, begitu banyak kapal besar dan kecil yang melintas, juga suatu pemandangan indah. Mereka membawa hasil kebun seperti kelapa, pisang dan sayur mayur. Para pelancong juga lewat dengan speedboat. Kami biasanya melambai-lambai kepada mereka, sambil mengucapkan selamat jalan seakan-akan kami sudah puluhan tahun saling mengenal dan sedih mengalami suatu perpisahan. Sungguh, betapa menyenangkan main di sungai itu.Karenanya, main di sungai harus dilakukan secara diam-diam. Biasanya, kami memulainya saat ibu-ibu kami lagi berjuang memasak atau mencuci di dapur. Jika masih ada beberapa ibu-ibu yang ngobrol di depan rumah, maka kegiatan menuju sungai juga harus diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mula-mula, kami main-main di ujung rumah yang paling dekat sungai. Jika dipastikan tidak ada satu pun orang tua yang melihat, maka kami dengan cepat melesat menuju sungai. Berlari pontang-panting bagai dikejar setan kuburan, dengan mulut terkunci dan sepasang sandal jepit tergenggam erat di tangan. Jika sudah sampai di sungai, baru kami berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Bagai meraih suatu kemenangan besar.Tetapi ritual aneh jenis ini juga agak sedikit berbeda jika dilakukan untuk mewujudkan aksi pulang ke rumah. Meski harus tetap waspada takut tertangkap basah, urusan lari atau tidak tergantung dari kondisi keramaian lingkungan rumah. Jika suasana sepi, maka tidak perlu begitu takut untuk berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Tetapi jika ramai, maka kami akan pulang pelan-pelan mengitari belakang rumah orang. Bila perlu melalui jalan memutar, tentu saja jika air sungai sedang tidak pasang. Karena jika pasang, akan sulit memanjat tebing beton untuk memasuki kawasan itu. Terpeleset bisa sukses masuk sungai. Tetapi jika tidak pasang maka akan mudah berlari di pasir, kemudian memanjat tebing tersebut. Rutenya memang melewati stadion Patrajaya dan kemudian masuk asrama lewat gerbang pengawalan. Jadi seolah-olah baru pulang dari rumah teman yang rumahnya di dekat jalan raya.Cuma bahaya ketika akan pergi, jauh lebih menakutkan dari bahaya menuju acara pulang. Bahaya pergi, jika ketangkap basah paling hanya diomeli. Tetapi jika bahaya pulang, justru bukan dari orang tua. Jika lewat belakang rumah orang, kondisinya sangat menyeramkan. Gelap, rawa, nyamuk dan bau busuk. Jika lewat Patra Jaya, harus waspada terhadap serbuan monyet-monyet aneh penghuni makam yang terletak tak jauh dari stadion sepakbola, bahkan ditengah-tengah lokasi lapangan golf. Konon itu bukan monyet sembarangan. Mereka hidup berkelompok dan berkegiatan bak manusia. Jumlah mereka konon selalu tetap. Sebab jika ada satu anggota baru (bayi monyet yang baru dilahirkan), maka satu monyet akan di depak dari komunitas itu. Monyet yang sudah keluar dari habitatnya ini biasanya datang ke pemukiman penduduk dan kemudian akan dipelihara orang buat jaga rumah, layaknya anjing atau kucing.
Sebenarnya monyet-monyet ini kalau kelaparan juga sering mendatangi rumah-rumah penduduk untuk cari makanan. Mereka memanjat pohon untuk makan jambu atau pisang seenaknya, bahkan kerak yang dijemur penduduk pun bisa dibawanya. Monyet-monyet ini memang hanya mengandalkan makanan dari sesaji yang diberikan para peziarah makam tua di Patra Jaya itu. Konon itu makam Putri Bagus Kuning berikut kerabatnya. Putri yang konon wujudnya bagus (sempurna) dengan kulit kuning langsat. Mungkin putri ini termasuk idola atau superstar di zamannya, sehingga menjadi rebutan banyak pria dan melegenda. Dan monyet-monyet itu konon adalah para dayang dan pengawal sang puteri yang tetap setia sampai keturunannya untuk menemani sang puteri ini.Tetapi ada juga yang bercerita, jika sekumpulan monyet-monyet itu tidak lain adalah keturunan Kero Rambang. Atau Kero (kera) dari Pulau Rambang. Mereka adalah sekelompok manusia yang dikutuk karena suatu kesalahan dan lari dari pulau tersebut. Karena malu, mereka berlindung di makam tua sang puteri yang konon angker. Karena itu, jika ada kelakuan manusia yang rakus, tidak tahu malu atau tidak berakal budi, maka orang sering menyebutnya bertingkah seperti Kero Rambang. Salah satu tindakan monyet tersebut yang dianggap tidak berperikebinatangan, adalah mengusir salah satu anggota keluarganya jika sudah terdapat anggota baru. Para monyet ini dianggap tidak mau populasinya bengkak. Mereka sudah menganggap habitat mereka itu sudah penuh sesak dan tidak punya niat untuk mempersempit wilayahnya lagi.Entah sistem apa yang digunakan untuk mengeluarkan anggota lama demi anggota baru ala para monyet ini. Mungkin secara voting, mufakat, atau mungkin juga diundi layaknya arisan. Yang jelas,hanya monyet-monyet tua yang bertubuh gemuk dan besar sepertinya tidak pernah ditemukan terlantar di pemukiman penduduk. Mereka selalu ada di komunitas itu. Mungkin juga para monyet besar dan tua ini tetap terus bertahan karena mengantungi hak veto. Atau mungkin sebenarnya monyet-monyet tua ini justru merupakan manusia yang dikutuk itu? (Wallahuallam!) Yang jelas, aku tidak pernah menghitung jumlah monyet-monyet itu. Jangan kan menghitung, melihatnya saja ngeri. Padahal para monyet ini pede sekali. Terutama jika ada acara di stadion, misalnya sepakbola, mereka tidak malu-malu juga ikut berbaur dengan penonton. Dan tidak malu-malu merampas makanan dan minuman orang. Makanya kami kadang berpikir lama baru memutuskan pulang lewat Patra Jaya. Monyetnya itu, lho! Hanya saja, biar ritual pulang ke rumah cukup sulit, tetapi acara bermain di sungai selalu menjadi kegiatan favorit.Seperti pagi itu. Kami memutuskan berenang di sungai, meski yang bisa berenang cuma dua orang. Vina dan Budi. Vina sudah kelas tiga SD, tapi dia sekolah siang. Dia paling besar diantara kami. Jamie yang terkenal sangat nakal tetapi murah senyum itu juga jago berenang. Sedang Budi, biar lebih kecil dari aku dia jago berenang seperti lumba-lumba. Dia sangat pemberani dan cukup pintar bicara. Sementara temanku yang lain, Doddy dan Eve juga sama seperti aku. Kalau berenang bisanya gaya batu, alias begitu menceburkan diri langsung tenggelam. Karenanya kami paling berenang sambil berpegangan di kayu-kayu besar bekas pohon tumbang. Kalau berenang, kami semua telanjang. Entah itu laki atau pun perempuan. Baju kami kami letakkan di rerumputan atau batu yang kering. Jika pulang dalam keadaan basah, maka sama saja membuka rahasia.Biasanya, aku memang takut dengan kedalaman sungai. Meski senang dengan air, aku takut menuju ke tengah sungai. Aku sudah cukup puas dengan bermain di pinggirnya saja. Tetapi hari itu, entah kenapa, aku iri sekali melihat Budi jungkir balik terjun ke sungai dan berenang sampai ke tengah. Rasanya aku begitu malu jika sampai tua nanti tidak juga mahir berenang seperti dirinya. Meski Vina beberapa kali meneriakkan kepada kami yang tidak bisa berenang untuk tidak ke tengah, tetapi aku diam-diam mencoba.Pertama, aku melepaskan peganganku dari pohon tumbang itu. Tetapi ketika aku seperti akan hanyut, maka aku kembali berpegangan. Itu terjadi berulang kali, hingga tiba-tiba aku sudah tidak bisa meraih pohon itu lagi. Kakiku pun tidak bisa menjejak pasir. Jauh-jauh…itulah yang kurasakan. Tiba-tiba aku merasa menjadi semakin jauh dengan teman-temanku. Aku berteriak menggapai-gapai.
“Vin! Vin!” aku memanggil-manggil Vina. Aku melihatnya mencoba menarik tanganku. Aku juga masih mendengar jeritan teman-temanku yang lain. Tetapi selanjutnya, yang kulihat dan kurasakan hanya air, air dan air.Entah berapa lama aku berada di dalamnya, sampai ketika aku merasakan semuanya sesak dan begitu menyakitkan. Aku mengepak, berlari dan menggapai kesana-sini. Mengharap pertolongan datang dari siapa pun. Sampai akhirnya aku memegang sesuatu, seperti rambut atau entah apalah itu. Dan ketika aku memaksakan diri untuk membuka lebar-lebar mataku, bathinku terenyuh.Oh, Tuhan. Aku hampir tak mempercayai mataku. Sosok itu…sosok yang mampu mengaburkan mata dan jiwaku. Kami bertatapan dengan situasi yang tak mampu kujelaskan. Tetapi aku ingat tatapan itu dan seakan mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Dia terus melaju dengan kuat ke permukaan, menyeretku dengan genggaman rambut ditanganku. Sinar matahari kurasakan semakin hangat ketika kepalaku menyembul diatas permukaan, membuatku mampu bernafas dengan kesetanan.
“Dapat! Dapat! Dhea selamat”
“Kau tidak apa-apa, Dhea?”
“Tarik! Tarik!”
“Cepat, sebelum dia kembali di tarik Antubanyu!”Aku mendengar suara-suara itu. Aku masih bingung dan kelelahan. Tetapi tangan-tangan itu menarikku dengan buas hingga aku tersungkur di pasir. Terbatuk-batuk hingga muntah. Setelah kurasakan penglihatanku pulih, aku baru terduduk diam di pasir. Di sampingku, tampak Vina, Jamie, Budi, Donnie, Doddy dan Eve ikut duduk dengan tubuh gemetaran.
“Kau melihatnya, Dhea?”
Aku terpana. Tetapi Budi mengangkat bahunya.”Sudahlah. Kami tadi melihat sesuatu di air. Apalah itu bentuknya, aku yakin itu yang namanya Antubanyu!”
“Budi!” Eve tampak merinding ketakutan.”Aku tidak lihat apa pun tadi”
“Ya, Eve tidak sempat lihat. Dia sibuk menangis” bela Doddy.“Kau beruntung, Dhea. Vina menyelamatkanmu tadi. Dengan berani dia berenang ke tengah untuk menggapai tanganmu. Kau tadi hanyut terbawa arus, timbul dan tenggelam dan tiba-tiba kau menghilang seakan ditelan ke dasar sungai. Tetapi beberapa saat kemudian kau muncul ke permukaan. Menyeruak bagai kesurupan. Ketika kami masih terpana, Vina dengan sigap menggapai tanganmu. Kalau dia tidak menarikmu cepat-cepat, kau sudah mati dimakan Antubanyu” terang Budi panjang lebar.Aku langsung menatap Budi dan Vina bergantian. “Kalian melihat sesuatu?”
“Aku lihat!” teriak Budi.
“Diam, Budi!” bentak Vina nyaris tertahan.
“Kalian lihat juga?” aku memandangi Doddy, Jamie dan Eve. Kulihat Eve menggeleng dengan jujur. Tetapi Doddy, dia tampak kebingungan. Sementara Jamie, gayanya yang cuek itu menyiratkan bahwa meski dia tahu tapi tak akan peduli apa itu.
Aku menghela nafas,”Tolong, kawan-kawan. Apa pun yang kalian lihat tadi. Apa pun itu. Jangan pernah bercerita kepada siapa pun”“Ya, jangan cerita apa-apa. Nanti orang tua kita marah jika tau Dhea sampai hanyut tadi di sungai. Kita kan main ke sungai ini diam-diam” kata Vina.
“Itu salah satunya. Terima kasih Vin, sudah menyelamatkan aku. Tetapi aku harap kau akan menyimpan cerita tentang kejadian ini selamanya. Kalian semua. Sampai kapan pun!”
“Kenapa?!” teriak mereka nyaris bersamaan.
“Pokoknya jangan cerita pada siapa pun kalau kalian ingin selamat”
“Kau mengancam kami?”
“Bukan aku”
“Lalu?”Aku mengalihkan pandangan ke sungai itu. Kini airnya bergelombang kuat. Seperti ketika sebuah kapal asing tiba-tiba lewat. Air sungai itu berderak menghantam batuan penahan air yang di bangun pada masa penjajahan Jepang itu. Angin pun tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan pasir-pasir hingga baju-baju kami yang tadi tergeletak bergelimpangan di rerumputan. Dan anehnya, cuaca yang tadinya panas tiba-tiba menjadi suram. Dan semakin mencekam ketika petir mulai menyambar-nyambar. Kami berlarian menjauh dengan ketakutan sambil sibuk menyambar pakaian masing-masing yang sudah bertebaran tak karuan. Dan aku, di tengah kekalutan itu, seperti kembali mendengar suara-suara. Suara aneh yang sempat kudengar sebelumnya. Suara samar tetapi terasa begitu nyaring melengking. Memekakkan telinga dan membuat kepala pusing.“Jangan bilang siapa-siapa soal kejadian ini! Berjanjilah! Kalau kalian bercerita pada siapa pun, maka akan terjadi sesuatu yang menakutkan pada diri kalian. Sangat menakutkan!” aku berteriak-teriak sekuat-kuatnya. Aku tahu teman-temanku itu bodoh dan mulutnya ember semua. Harus ada kekuatan besar untuk menyadarkan mereka pentingnya untuk menjaga suatu rahasia.“Ya! Ya! Kami berjanji” mereka kemudian kudengar pula berteriak-teriak kepadaku. Semuanya. Aku lega. Setidaknya mereka telah berjanji untuk tidak bercerita. Aku percaya kepada mereka
Aku tidak tahu lagi apa sesungguhnya yang terjadi kepadaku selanjutnya. Aku merasa tubuhku panas dan bergetar hebat. Tetapi sebelum semuanya kurasakan menjadi gelap, aku masih mendengar suara-suara teman-teman kecilku yang kembali menjerit-jerit ketakutan.
“Kesurupan! Kesurupan!”
***Tak ada yang tahu banyak soal peristiwa itu. Untunglah, teman-temanku itu merahasiakannya terutama dari keluargaku. Entah mereka takut soal pesanku atau takut juga kena getahnya. Tetapi saat aku pingsan mereka dengan setia menungguiku. Kami berteduh di reruntuhan gedung bekas restoran pinggir sungai. Padahal lokasi itu sebenarnya sangat membahayakan karena nyaris runtuh. Dindingnya sebagian sudah retak dan sebagian lagi sudah benar-benar runtuh mencium tanah. Tetapi rasa ketakutan teman-temanku atas kemarahan orangtua masing-masing mengalahkan ketakukan akan dihantam keruntuhan gedung tua itu.“Syukurlah kau sudah sadar” terdengar suara Vina, “Pusing?”Vina tertawa kecil dan yang lainnya ikut-ikutan cengengesan. Kekacauan tadi sudah berakhir. Tak ada lagi angin apalagi hujan. Cuaca juga mulai cerah lagi.
“Kita pulang!” tiba-tiba suara Budi memecah. Kemudian terdengar sorak-sorai yang begitu keras seperti akan meremukkan reruntuhan bekas restoran itu. Seakan tersadar dari kekacauan panjang, kami kemudian berlarian liar menuju rumah. Sekuat tenaga seakan mengejar sesuatu.“Tadi kau seperti akan mati saja” Vina tertawa-tawa ketika kami berlari-lari di jalan setapak.
“Iya, matamu melotot dan kau berteriak-teriak” sahut Budi.
“Ah, dia cuma ketakutan” sambung Jamie sambil berjingkat-jingkat menggoda Doddy yang berlari kecil di sebelah Eve.
“Tidak, dia…”
“Hei, apa yang kau pegang?”
“Apa?” aku berhenti berlari. Kedua tanganku lalu kuangkat ke muka. Dan aku baru menyadari, jika aku memegang sesuatu di tangan kananku. Sesuatu yang panjang, keras dan seperti ijuk namun sedikit berlendir.
“Itu rambut!”
“Rambut siapa ini? Aku kan…”“Antu Banyu …”suara itu, suara salah satu dari kami. Tetapi yang terdengar malah lebih mirip suara lain dari dunia yang lain. Sebelum kami menyadarinya lebih jauh, kaki-kaki kecil kami seakan tak dapat ditahan untuk segera berlari. Menjauh dan menjauh.
“Jangan katakan ini kepada siapa pun!” aku kembali berteriak sambil terus berlari. Tetapi aku yakin, tak ada satu pun dari mereka yang mendengar.
***
Aku bangun di pagi itu dengan kebingungan. Ibu pagi-pagi sudah menghilang dan bukan ke warung. Saat aku ke luar rumah, para tetangga sibuk berlarian ke satu arah. Sebelum aku sempat bertanya, ibu kulihat berlari-lari menghampiriku.
“Mandi! Mandi!”Dan di dalam kamar mandi itu, aku diberikan ceramah panjang lebar. Soal tidak boleh main di jalan raya, tidak boleh pergi-pergi tanpa izin orang tua sampai jangan mau diajak orang asing.
“Kenapa sih, Mak?” tanyaku pada Ibu. Kami memang kemudian lebih terampil memanggil Ibu dengan sebutan Emak. Padahal sebelumnya kami diajarkan untuk memanggil orang tua kami dengan sebutan Ibu dan Ayah. Tetapi lingkungan merubah segalanya. Karena di lingkungan kami banyak orang menyebut ibunya sebagai “emak”, Layaknya orang melayu, orang tua biasa disapa dengan sebutan emak dan ayah. Maka kemudian berubahlah panggilan itu. Bahkan karena lingkungan juga, aku bahkan pernah memanggil ayahku dengan sebutan “Pak-e” karena tetanggaku kebetulan juga ada yang dari Jawa. Meski kemudian hal itu tidak berlanjut, karena ayah tetaplah disebut ayah. Tetapi dikemudian hari (lagi-lagi) karena lingkungan juga, saat remaja kami kerap memanggil ibu kami dengan sebutan “mami”. Hanya saja, sebutan itu sering kami lontarkan kalau kami sedang sebal mendengar omelannya.Balik lagi ke pagi hari yang aneh itu, rupanya pertanyaanku tidak langsung dijawab ibuku. Dengan hati-hati sekali beliau menjelaskan sesuatu yang sulit kupahami. Untuk pertama kalinya aku tahu, bahwa manusia itu pasti mati. Hany, putri kesayangan tetangga kami tewas dalam kecelakaan di jalan raya saat akan menyeberang jalan menuju ke sekolah. Ada tiga teman sekolahnya yang juga ditabrak saat itu. Dua temannya parah semua. Ada yang patah kaki, yang lainnya malah patah tangan. Tetapi Hany, anehnya dia tidak luka sedikit pun. Dibanding teman-temannya yang terpaksa di rawat di rumah sakit, Hany diperbolehkan pulang ke rumah. Cuma setelah di rumah dia mengeluh pusing di kepala dan minta tidur. Tetapi kemudian dia malah muntah-muntah dan akhirnya kembali di bawa ke rumah sakit. Sayang, Hany kemudian meninggal.Kami berdiri berderet-deret di jendela rumahnya. Mengintip jenazah Hany yang di bawa ke rumah. Ada rasa ketakutan karena beberapa teman membisikkan bahwa orang yang meninggal arwahnya akan menjadi setan. Setan dalam pikiranku tentu sangat menakutkan. Karena aku pernah melihat contoh setan itu saat nonton film horor di tempat tetangga kami yang punya video dan kerap mengutip biaya nonton bak bioskop. Tetapi yang lebih menarik lagi, adalah bisikan teman-teman tentang satu lemari penuh mainan milik Hany yang kami lihat tepat berada di dekat jendela itu. Suatu hal yang tidak akan dinikmati lagi oleh anak kesayangan keluarganya itu. Aku melihat mainan-mainan itu. Ada boneka, mainan peralatan masak, keyboard hingga drum kecil.Yang terakhir itu, suatu mainan yang begitu menarik dalam penglihatanku. Meski semua mainan itu tentu saja menarik bagi anak seusiaku dan bernasib kurang beruntung seperti aku. Sebanyak-banyak mainan yang pernah kumiliki, adalah warisan dari mainan kakak-kakakku. Tak ada kesempatan bagiku untuk menikmati indahnya dibelikan banyak mainan seperti itu karena krisis keuangan di keluargaku saat itu. Aku hanya ingat, ayah pernah membelikanku gitar kecil dari plastik dan ibu pernah membelikanku keranjang mungil isi telur plastik suatu mainan yang hingga remaja aku masih menyimpannya. Meski gitar itu patah karena dibanting sepupuku dan akhirnya keranjang itu jadi penghuni dapur sebagai tempat meletakkan korek api.
Dan kenangan akan drum mungil milik itu, menjadi kenangan tersendiri dalam kehidupanku. Mainan yang mungkin bertahun-tahun kemudian tetap ada di lemari kaca itu, meski pemiliknya sudah terbang ke alam baka. Keluarganya mungkin menyimpan itu untuk sebuah kenangan. Dan mungkin, mereka tidak pernah tahu, jika beberapa meter dari rumah mereka ada seorang anak kecil yang begitu menginginkan mainan itu. Soal mainan itu, masih terkenang-kenang sampai aku dewasa. Tetapi sebenarnya, bukan soal mainan itu saja.Tidak begitu lama dari kematian Hany, peristiwa lain datang lagi. Aku masih ingat, hari itu semuanya baik-baik saja. Aku mengakui, Jamie memang cukup jahil dan nakal. Bagi anak-anak kolong setempat, bocah peranakan bule itu memang cukup disegani sepak terjangnya. Jarang ada yang mau bermain dengannya dalam waktu yang cukup lama. Bahkan terkadang dia tidak diizinkan untuk ikut bermain. Tetapi tampaknya Jamie tidak terlalu merasa dikucilkan. Kalau diusir, dia paling hanya tertawa-tawa saja. Dia cukup puas dengan pola permainannya sendiri. Bahkan dia juga tidak mau melibatkan dua saudaranya, Flora dan Donnie untuk turut bermain dengannya.Tetapi bagiku, sebenarnya Jamie tidak benar-benar menjengkelkan. Meski aku agak risih dengan tampangnya yang sedikit bule itu (konon nenek buyutnya ada keturunan Belanda), namun Jamie cukup mengagumkan. Dibalik rambutnya yang pirang, kulitnya yang pucat kusam kemerahan dan bibirnya yang aneh (meski merah tapi tebal, besar dan lebar), Jamie merupakan anak hebat. Dia sangat pintar membuat mainan. Keahlian itulah yang kadang membuat banyak teman kadang bisa juga sedikit simpati, bahkan bersedia menukar mainan buatannya itu dengan uang atau makanan. Yang kuingat, Jamie jago sekali membuat sesuatu dari tanah liat. Dia bisa membuat patung, peralatan masak dan masih banyak lagi. Dan karyanya yang paling monumental dan mungkin yang terakhir kalinya adalah televisi dari tanah liat. Benar-benar luar biasa, nyaris seperti aslinya.Jamie menciptakan televisi tanah liat itu, setelah teman-teman tidak mengajaknya bermain di rumah kosong (salah satu rumah tentara yang kosong karena penghuninya pindah tugas). Dia diusir dengan kasar karena dianggap terlalu liar untuk berada dalam komunitas yang sama. Seperti biasa, si cuek itu cuma cengengesan. Berlalu dengan santai dan bermain di pekarangan rumahnya, tepat di bawah pohon nangka besar. Suatu tempat yang telah menjadi saksi karya-karya spektakulernya. Tetapi beberapa saat kemudian, seorang teman berteriak-teriak dengan penuh kekaguman.
“Hei, Jamie membuat tivi! Bagus, bagus sekali!”Belum sempat kami berlari ke depan rumah Jamie, dia sudah datang memamerkan televisinya itu. Dan respon teman-teman pun langsung berubah. Mereka mulai merayu-rayu Jamie untuk minta dibuatkan mainan serupa. Meski sudah diusir, Jamie tampaknya tidak sakit hati. Mungkin dia sudah cukup puas melihat teman-teman mulai mengemis-ngemis kepadanya minta dibuatkan televisi dari tanah liat. Dan sampai siang itu, Jamie sibuk menerima order pembuatan televisi.“Jamie, buatin aku juga ya” pintaku penuh harap. Ketika dia sudah menyelesaikan beberapa televisi tanah liat pesanan teman-teman.
“Ya, nanti. Besok ya!’ katanya dengan mantap. Lagi-lagi aku melihat dia cengengesan. Menampilkan deretan giginya yang mulai hitam berkarat.Ternyata, janji Jamie itu tidak pernah terpenuhi. Di pagi hari itu, kembali aku melihat salah seorang temanku mati. Suatu hal yang sangat mengagetkan, karena kemarin Jamie tidak terlihat sakit. Dia justru begitu bersemangat membuat televisi tanah liat. Meski takut, aku melihat Jamie sudah dalam keadaan dikafani. Kain kafan putih yang membungkus tubuhnya itu selalu kukenang. Sebagaimana aku mengenang ritual aneh menjelang mayatnya di bawa ke pekuburan. Di tengah gerimis itu, ibunya menyerahkan sepiring beras kuning kepada seorang bapak tua. Bapak itu lalu menaburkan beras itu diatas keranda mayat, tetapi anehnya kemudian membanting piring itu ke batu. Terdengar jeritan para wanita di sana-sini. Aku pun, yang terang-terangan ada di dekat lokasi tersebut bahkan meloncat ketakutan karena serpihan pecahan piring itu nyaris menghantam kakiku.Dan sore itu, kami kehilangan bocah unik yang sebenarnya mungkin sangat berbakat menjadi seniman perupa. Bisik-bisik yang kudengar dari para ibu-ibu tetangga yang bergosip seharian, Jamie meninggal karena habis disiksa ayahnya. Ayahnya yang tampan tetapi sangat pendiam dan tertutup itu konon kesal karena Jamie melakukan kenakalan yang menurutnya sulit dimaafkan. Apalagi saat dipukul sang ayah, Jamie balas memukul dengan tak kalah kerasnya. Seperti kesurupan.“Sakit itu bapaknya kena tonjokan si Jamie. Entah, Jamie kesurupan setan mana. Dia kuat melawan bapaknya”
“Memang bapaknya agak aneh ya. Seperti tidak mau mengenal orang lain. Tertutup sekali. Tetapi saya tidak yakin dia tega memukul anaknya sampai mati”
“Salah satu diantara mereka, bapak dan anak itu pasti ada yang kemasukan setan”
“Setan? Setan mana?”“Ya, mana aja. Kan kita ini tinggal di dekat sungai. Sungai yang sering makan korban. Tiap tahun pasti ada orang yang mati. Kalau buaya yang makan pasti mayatnya udah masuk ke dalam perut. Tapi ini, masa mayatnya bisa diketemukan dalam keadaan kepala yang bolong? Mahluk apa yang bisa menyedot ubun-ubun kepala manusia hingga isi kepalanya kopong?”
“Kau jangan asal bicara, aduh, ampun mbah buyut…penunggu sungai…saya tidak mendengar apa pun!”Ibu-ibu itu kemudian berlarian masuk rumah. Suatu hal yang jarang terjadi. Aku pun segera ikut berlari pulang karena ayahku sudah mengajak untuk sholat berjamaah. Memang, meski menjelang maghrib tetapi ibu-ibu disana biasanya tetap ngerumpi.Bapak-bapaknya juga masih nongkrong di luar rumah. Berbeda dengan keluargaku yang dididik ayah secara ketat soal agama. Sholat maghrib berjamaah menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh anggota keluarga. Bahkan anak-anak tetangga terkadang ikut-ikutan shalat juga dengan keluarga kami karena orang tuanya tidak pernah shalat. Memang hanya segelintir para tetangga yang menjalankan pendidikan agama seperti keluarga kami. Bahkan aku masih ingat, beberapa tetangga kami masih menganut paham animisme. Meski KTPnya muslim, mereka rajin memberikan sajenan (sesaji) bagi roh-roh leluhur terutama pada saat malam jumat. Karenanya, kami sudah biasa melihat hal-hal aneh. Misalnya, kakakku pernah melihat keris melayang-layang di atas rumah tetangga. Atau ibuku mendengar ada yang mengamuk di rumah tetangga, padahal penghuninya sudah pindah. Kata ibu, para setan di rumah itu sedang kesal karena sudah tidak ada yang memberi sajenan lagi.Untuk urusan perbedaan paham ini, ayahku jawabannya. Ayah pernah membubarkan perguruan beladiri yang dipimpin tetangga, hanya karena melihat yang belajar ilmu itu jadi pada kesurupan semua. Seperti kemasukan setan, saat belajar ilmu itu mereka sering mengamuk, mencakar, mengais seperti harimau lapar. Dan menurut ayah, ilmu tersebut tidak diajarkan di dalam Alquran.“Terserah, apa kalian mau jadi harimau atau mau jadi setan. Tetapi jangan sekali-kali mengembangkan ilmu itu di sebelah rumahku!” teriak ayah dihadapan tetangga yang mengajarkan aliran menyeramkan itu.Puluhan anak-anak yang belajar beladiri aneh itu kemudian bubar. Dan tetangga kami yang mencoba mengembangkan kegiatan itu pun mendadak jadi pindah rumah. Mengisi rumah tentara lain yang kebetulan kosong. Tidak ada benturan yang terjadi. Semuanya berakhir damai. Toh, para orangtua yang anaknya sempat belajar ilmu aneh itu juga malah bersyukur atas pembubaran itu. Meski demikian, hal mistis masih saja terus membingkai kehidupan di lingkungan kami.Seperti seminggu setelah Jamie meninggal, Dian, Johan, Hery dan Tuti menceritakan sesuatu yang berbau mistis dan membuatku merinding.
“Tantri, Indri dan Hany itu sehari sebelum kecelakaan sempat bertemu dengan Jamie. Bahkan Hany sempat ngobrol dengan Jamie. Aku melihatnya kok pas mau main ke rumah Nino. Tanya aja dengan si Hery. Eh, besoknya Hany meninggal. Terus, Jamie juga ikut-ikutan mati kan?” kata Dian.“Iya, Her?” tanyaku pada gadis hitam manis yang kalau bermain senang menirukan gaya wanita karir itu. Dan si Hery mengangguk. Aku tahu, dia anak yang jujur. Aku paling senang bermain dengannya karena dia terlalu lugu.
“Mereka saling ajak ya?” kata Johan.
“Masa sih?” Tuti yang paling kecil itu mengkerut takut.Dan jawaban selanjutnya kudapat dari Tantri yang sudah pulang dari rumah sakit. Kaki kirinya masih digips dan dia masih sulit berjalan. Agak membingungkan aku jika Tantri dan kawan-kawannya tiba-tiba bisa ngobrol dengan Jamie. Rumah mereka cukup jauh dari rumah Jamie dan mereka juga bukan teman sebaya. Hal yang cukup langka jika tiba-tiba mereka menyempatkan waktu ke rumah Jamie.“Waktu itu kami ada keperluan dengan kakak Jamie, Flora. Kami kan teman satu sekolah. Kami ada kegiatan menari dan Flora itu kan kepengen banget jadi artis. Kami pikir dia cocok untuk bergabung dalam kelompok tari itu. Ya, sekarang boro-boro nari, jalan saja susah” kata Tantri sambil tertawa. Seakan dia lupa kalau kakinya pernah patah dilindas roda mobil. Dia memang selalu tampak gembira. Mungkin itu bawaan dari keluarganya yang selalu murah senyum itu.
Dulu kata kakak dan ibuku, sebelum masuk SD Tantri gemar main ke rumahku. Dia anak yang sangat sederhana dan tidak banyak tingkah. Konon, dia tetap makan meski hanya diberi sepiring nasi dingin dan sebiji jengkol mentah saja. Cerita ini kerap diulang ibuku, jika kami kakak beradik sering ribut soal makanan.“Jangan terlalu banyak memilih soal makanan. Apa pun yang ada di makan asal halal. Karena belum tentu kita punya kesempatan makan terus. Jika kita tidak punya cukup uang untuk makan, maka kita harus siap makan dengan alakadarnya. Tantry itu contohnya, tidak pilih-pilih soal makanan. Dia tidak sombong apalagi takabur. Bayangkan, anak sekecil itu dikasih nasi dengan jengkol mentah aja mau” pesan ibu.Suatu pesan yang sulit kami jalankan. Karena meski kami tidak pernah dibelikan barang-barang mahal, tetapi untuk urusan makan di rumah nomor satu. Dari pagi buta hingga malam, menjelang nasi plus lauk-pauk terhidang lengkap. Ibuku terkenal rajin membuat beraneka ragam kue yang mengundang selera. Setiap hari ada variasinya. Alasan ibu, biar kami tidak rewel minta jajan di luar. Karena jajan berarti boros dan belum tentu jajanan itu bersih. Kalau kotor, nanti berpenyakit, lalu masuk rumah sakit dan artinya tentu bakal mengeluarkan biaya …
Dan Tantry juga membenarkan soal besarnya pengeluaran biaya keluarganya saat dia masuk rumah sakit. Meski biaya perawatan ditanggung pemerintah karena bapaknya tentara, tetapi ada banyak biaya ekstra yang tak terduga.“Biaya makanan tambahanku seperti buah, susu dan lain-lain biar cepat sehat. Biaya ongkos transportasi keluargaku yang membesuk dan menjagaku, belum makannya mereka masing-masing. Banyak deh! Kasihan bapakku. Untung nenek dan paman membantu untuk urusan biaya ini. Ah, pokoknya ingin cepat sembuh deh” ungkap Tantry.
“Kenapa bisa kecelakaan?”“Tau juga tuh. Kita kan bertiga mau nyebrang. Biasanya kami kan minta bantuan oom-oom di pengawalan (tentara yang bertugas menjaga gerbang asrama). Tetapi mungkin karena kami tidak sabar jadi kami nyeberang sendiri. Mulanya ragu, eh, terus kita lari-lari. Tiba-tiba ada mobil dan ..gitu deh”“Nggak ada yang aneh?”
“Aneh?” Tantry berpikir sebentar.”Ya, aneh juga sih. Kayaknya saat lari-lari itu satu dari kita ada yang jatuh. Terus kita bantuin supaya berdiri, tetapi kayaknya kaki kita lengket diatas jalan raya itu. Nggak bisa jalan apalagi lari. Tahu-tahu udah dihajar mobil”
“Kaki lengket di jalan? Ada hal aneh lain tentang Hany?”
“Ya, dia ditengah. Kan dia yang jatuh. Tapi dia tidak luka, tidak apa-apa. Malah dia sibuk bantuin aku dan Indry yang luka parah. Tahu-tahu dia meninggal ya. Sedih banget rasanya. Kena gegar otak mungkin dia”“Ya, aku juga sedih kehilangan Jamie. Mungkin dia nakal, tapi dia sebenarnya tidak pernah terlalu jahat. Terutama padaku, seingatku dia tidak pernah jahat”
Tantry mengangguk,”Ya, aku mungkin baru satu kali itu ngobrol dengannya. Oh ya, dia jago buat patung-patung dari tanah liat ya? Bagus sekali karyanya itu. Saat menunggu kakaknya di depan rumah, kami ngobrol soal kehebatannya membentuk tanah liat itu. Itu pasti bakat alam, karena orang tuanya kan nggak ada yang seniman? Atau mungkin neneknya yang bule itu kali ya”“Mungkin. Aku memang lebih akrab dengan adiknya, Donnie. Dan Flora lebih akrab dengan kakakku Liza. Tetapi Jamie sendiri memang tidak terlalu suka bicara. Dia lebih banyak cengengesan”
“Iya, benar. Dia tertawa terus. Hany sangat suka dengan karya-karyanya. Bahkan dia berkeinginan untuk minta dibuatkan mainan dari tanah liat dan akan disimpannya di lemari kaca”Aku menghela nafas. Oh, lemari yang menyimpan mainan drum kecil itu.
“Lalu, Jamie mau membuatkannya sesuatu dari tanah liat itu?”
“Mungkin. Habis mereka bicara berdua saja. Aku dan Indry sibuk ngobrol dengan Flora. Ya, kalau pun Jamie berjanji membuatkannya juga tidak ada gunanya. Besoknya Hany mati, dan kini Jamie juga ikut-ikutan dikubur”
“Jadi kamu tidak tahu mereka membicarakan apa saja?”
“Nggak. Eh, memang kenapa?”
“Eh, anu…”aku gelagapan.Aku khawatir dia mencurigai aku. Mungkin karena aku masih lima tahun mestinya tidak usah terlalu sok tahu urusan begitu. ”Kata teman-teman, biasanya orang yang mau mati itu bisa saling ajak. Kan akhirnya mereka mati dalam waktu yang berdekatan?”
Tantry mengangguk-angguk,”Ya, mungkin juga”
Oh, Tuhan. Syukurlah.
“Tapi tunggu! Kalau tidak salah, mereka membicarakan tentang sungai”
“Sungai?!” nafasku seakan terganjal di tenggorokan.
“Ya, ya. Sungai atau apalah itu. Masalahnya aku sempat dengar Hany bertanya dari mana Jamie memperoleh tanah liat itu”“Dari kebun pisang dekat sungai …” tebakku. Karena aku ingat, Jamie pernah menunjukkan lokasi tanah yang pernah digalinya untuk mengambil tanah liat itu.
“Aku mengambil tanah lempung (tanah liat) disitu!” ujar Jamie waktu kami sedang bermain di sungai. Lokasi kebun pisang tempat penggalian tanah itu memang berada sekitar sepuluh meter dari tepi sungai. Malah kalau air sungai sedang pasang, kebun pisang itu juga kebanjiran.
“Ya, begitu!” Tantry membenarkan dengan penuh semangat. “Terus Hany bertanya apakah dia tidak takut mengambil tanah liat sendirian di sungai”
“Jamie jawab apa?”“Aku tidak tahu. Tapi aku yakin jawabannya tidak. Buktinya kan dia membuat banyak mainan dari tanah liat. Pasti setiap hari dia ke sungai mengambil tanah liat itu”
Ya. Jamie tidak takut apa pun. Bathinku. Mungkin juga dia tidak takut meski pernah melihat mahluk air itu. Dan tidak terlalu ragu untuk bercerita tentang sosok itu pada seorang Hany yang begitu mengagumi hasil karya tanah liatnya.Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Setelah pulang dari rumah Tantry tadi, aku langsung lari ke rumah. Dengan hati-hati aku membuka tas kecil kuning hadiah ayah waktu tugas di Bangka. Sesuatu itu, masih ada disana. Tidak lagi basah, tetapi kering seperi ijuk. Sejak kejadian di sungai itu aku masih menyimpannya. Terkadang aku membuka tas tersebut hanya karena ingin melihat “sesuatu” itu.Dan sejak kejadian di sungai itu, entah kenapa, aku selalu ingin kembali kesana. Entah itu bersama teman-teman atau hanya sendiri saja. Bahkan saat malam tiba, aku langsung merangkak di bawah ranjang kakak-kakak laki-laki, dimana ada nenekku yang tidur lelap disana. Nenekku yang bertubuh jangkung dengan rambut perak dan mata kelabu yang entah warisan dari mana itu memang gemar sekali tidur di bawah ranjang. Suatu kebiasaan yang menurut kami sebenarnya kurang wajar tetapi beliau enggan menjelaskan.Dan ketika kemudian aku meniru kegemaran nenek ini, hampir semua keluarga juga menentang. Sebelum aku terlena ikut tertidur bersama nenek, biasanya nenek juga langsung ribut untuk menyuruh aku pindah kamar. Jadi aku pasti akan tetap tidur bersama ibu dan kakak perempuanku (sementara ayah tidur di ruang tamu), karena nenek pasti “mengusirku” jika aku sudah terlihat mengantuk disampingnya. Kamar itu terletak di sebelah dapur. Ruangan sambungan, karena batas rumah tentara memang tidak dapat dikatakan besar. Otomatis dengan penghuni rumah mencapai tujuh kepala, maka ayah terpaksa membangun ruangan baru alakadarnya dari kayu.Semua tentara disitu, umumnya membangun dapur atau kamar tambahan di belakang rumah. Karena biasanya terbuat dari kayu, maka kondisi kekuatan bangunan itu tentu tidak akan dapat dikatakan mampu bertahan lama. Gampang lapuk oleh hujan dan remuk oleh rayap-rayap yang bermukim disana. Karenanya, ketika suatu hari ayah menemukan selembar dinding dari anyaman bambu yang biasa kami sebut gedhek, maka tepat di sebelah kamar kakak dan nenek itu gedhek itu diletakkan. Dan dari bawah ranjang nenek itu, aku akan menyibak sudut-sudut gedhek yang tidak teranyam rapat. Dari lobang-lobang selebar kuku itu aku akan melihat pemandangan yang sangat indah.Pertama, kandang ayam milik tetangga. Lalu, kolam-kolam ikan, wc tradisional diatas got-got yang penuh ikan kopi-kopi, sepat serta belut. Juga ada pohon pisang, pohon waru, dinding stadion Patra Jaya, lokasi produksi air minum dimana diatasnya penuh lampu yang terang benderang. Dan jauh disana aku juga kadang melihat lampu-lampu lain dari kapal-kapal asing. Aku bahkan dapat mendengar jelas suara raungan speedboat, rengekan perahu gethek hingga debur ombak sungai yang pecah berderai menghantam batu-batu besar. Terkadang jika aku larut dengan semuanya, maka aku akan mendengar suara-suara yang terasa aneh ditelinga…***
Saat aku duduk di kelas dua SD, ayah pensiun. Kami lalu pindah di rumah kecil sederhana hasil kerja keras ayah. Lokasinya hanya seratus meter dari asrama tentara. Saat melihat rumah itu, rasanya aku maklum mengapa selama ini ayah selalu menjalankan pola hidup melarat sejahtera. Ternyata ayah ingin membangun rumah sederhana dari tabungan keluarga yang jumlahnya tidak seberapa. Dari uang itu, ayah membeli tanah yang sebelumnya berupa hutan rimba. Lokasi itulah yang dulu merupakan arena permainan anak-anak laki-laki asrama yang sudah besar. Hutan lebat menakutkan tetapi membuat penasaran.Aku ingat, ketika pertama kali ayah “meratakan” hutan itu untuk membuka lahan itu ayah menebas dan membakarnya. Aku masih sempat melihat begitu banyak ular yang ukurannya mulai dari sebesar tanganku hingga sebesar paha orang dewasa terpanggang karenanya. Bau daging panggang begitu menyengat. Bahkan sampai beberapa hari kami masih melihat bangkai ular yang garing itu. Mirip daging ikan asin gabus.Dan disanalah ayahku membangun rumah. Sebelumnya tanah itu ditanami dulu berbagai hasil kebun seperti kacang tanah, singkong, lengkuas dan kelapa. Setelah tabungan ayah dirasa cukup, kemudian beliau membangun sendiri rumah itu. Dengan kedua tangannya sendiri. Karena ayah tidak punya cukup uang untuk menggaji tukang. Ayah juga bukan tukang yang hebat, beliau hanya seorang ayah yang nekad. Seorang ayah yang tidak ingin nasibnya keluarganya tidak jelas setelah dia pensiun. Maka beberapa tahun menjelang pensiun, dia jungkir balik membangun rumah impiannya. Bertanya disana-sini dengan orang-orang yang pakar membangun rumah. Sepulang dari kantor, ayah langsung bergelut dengan semen dan batu bata. Dua anak lelakinya yang masih remaja ikut membantunya, bersama sang istri tercinta. Terkadang aku dan kakak perempuan ikut membawakan ayah seember pasir atau sebiji batu bata. Tetapi biasanya, kedatangan kami ini lebih sering merepotkan saja. Terutama aku, yang masih kecil dan terlalu sering ingin tahu dan senang mengacaukan segalanya.Membangun rumah memang tidak mudah. Dana terkuras meski biaya sudah ditekan disana-sini. Pasir ayah membelinya dari para bocah-bocah kecil yang mengeduknya dari sungai. Mereka adalah bocah-bocah pemberani yang hidupnya jauh lebih susah dari kami anak tentara berpangkat rendah. Aku ingat, usianya lebih muda dari kakak-kakakku. Rumah mereka jauh bahkan berkilo-kilometer dari kami. Sepulang sekolah mereka berkumpul di sungai demi mengeruk pasir untuk di dorong dengan gerobak kayu kecil ke rumah kami di asrama tentara itu. Mereka memang sudah biasa bekerja mengumpulkan pasir. Masalah ekonomi di keluarga mereka masing-masing, mendorong mereka untuk lebih kuat dan cepat dari usia sebenarnya dalam mencari uang.Dan menjelang maghrib, mereka akan berbaris rapi di ruang tamu. Sebagian duduk malu-malu di atas kursi kayu rotan hasil anyaman ayah. Lalu ayah yang sudah rapi dengan baju kemeja lengan panjang dan sarung, karena akan segera shalat maghrib, akan tersenyum lebar dan menggoda mereka dengan uang kertas atau logam. Sebelum membagikannya, ayah selalu memberikan petuah. Misalnya, agar tidak memfoya-foyakan uang upah mengumpulkan pasir karena lebih baik ditabung atau diberikan ke ibu masing-masing. Juga ada pesan agar hati-hati jika berada di sungai dan minta izin orang tua jika akan pergi bekerja. Sebagai tambahan, Ibu juga sering membuat penganan untuk dibagikan kepada mereka. Kemudian, ditengah keremangan malam mereka pulang dengan berboncengan naik sepeda ke rumah mereka yang jauh disana dengan penuh rasa gembira. Karena dikantung celana mereka ada potongan kue serta beberapa uang kertas dan logam.Aku terkadang memperhatikan kelompok bocah kecil pengumpul pasir ini. Mereka nampak lucu dan ramah-ramah. Kalau mendorong gerobak pasir mereka akan tertawa-tawa gembira, seakan itu bukan suatu beban dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka sering saling bercanda sehingga pekerjaan itu tidak ubahnya arena permainan saja. Beberapa dari mereka ada yang sering mengajak aku bicara. Tetapi sebagian biasanya hanya tersenyum jika kebetulan melihatku berdiri di depan rumah. Kepada mereka yang mau bicara itu, aku terkadang menanyakan rumah, sekolah atau saudara-saudara mereka seperti layaknya petugas sensus saja. Tetapi setelah sedikit akrab, aku kemudian berani menanyakan soal pasir yang selama ini telah mereka kumpulkan dari sungai.“Boleh aku melihat kalian mengumpulkan pasir?”
“Jangan! Nanti bapakmu marah. Bisa-bisa kami ditembaknya” kata salah satu dari mereka.
“Memang kenapa ayahku mau menembak kalian?”
“Bapakmu kan tentara”
“Biar pun tentara, tetapi di rumah ayah tidak pernah kulihat bawa senjata”
“Ah, pasti disimpannya di tempat yang kau tidak tahu”
Aku berpikir sejenak. Ya, mungkin juga. Tetapi aku tidak yakin ayahku gemar menembak orang. Biar beliau terkesan galak, kurasa otaknya masih baik-baik saja.
“Kalian kan sering ke sungai. Apa kalian tidak melihat sesuatu?’
“Sesuatu apa?”
“Apa saja!”
“Maksudmu buaya?” lalu mereka berdiri merapat. Seperti tim sepakbola yang sedang menanti tendangan pinalti.
Tiba-tiba salah seorang dari mereka mendekatiku sambil berbisik,“Atau Antu Banyu?”
Aku mundur selangkah. Mereka tertawa tergelak-gelak.
“Tanyalah pada pasir-pasir yang kami bawa itu. Mungkin dapat bercerita. Ah, kau ini ada-ada aja. Ini kan bukan bulan Desember dimana Antu Banyu minta tumbal”Mereka terus tertawa-tawa, sambil memindahkan pasir dari gerobaknya. Tampaknya mereka baru saja mendapat hiburan pelepas lelah. Dan sejak itu, aku tidak pernah bertanya-tanya lagi.
Seperti kata mereka, aku lebih baik bertanya pada pasir. Aku memang kemudian sering memandangi pasir di depan rumah yang dari hari ke hari semakin menggunung itu. Dimana terkadang aku juga serasa mendengar suara ombak, suara kapal dan suara-suara ‘itu’. Jika kemudian gunungan pasir di depan rumah itu menjadi kian menyusut, itu berarti para bocah pengumpul pasir itu telah usai menunaikan tugas. Mereka telah mendapat upah terakhir dan mencari majikan baru, orang-orang yang akan membangun rumah dengan biaya seadanya. Sementara ayah dan kakak sudah memindahkan gundukan itu ke lokasi bakal rumah baru. Pasir itu bercampur semen untuk merapatkan batu bata itu. Membentuk dinding sederhana di bakal rumah masa depan kami. Kata ayah, yang penting kami tidak kehujanan dan kepanasan.Dan di dinding yang di dalamnya tercampur pasir sungai itu, aku seakan merasakan sesuatu itu selalu ada di rumah kami. Bahkan bertahun-tahun kemudian. Meski aku pergi merantau begitu lama dan jarang kembali, aku seakan tahu jika tak perlu pergi ke sungai untuk merasakan sesuatu itu. Kelak, ketika kami telah benar-benar menghuni rumah itu, terkadang aku selalu merapatkan telinga ke dinding jika malam tiba. Disana aku seakan menikmati suasana sungai yang sebenarnya. Seperti aku benar-benar telah mengarunginya bahkan sampai ke dasarnya. Tetapi melintas diatas sungai Musi baru benar-benar kurasakan ketika usiaku telah menginjak 29 tahun. Karena suatu tugas dalam pekerjaan jurnalisku, meliput berita beberapa wakil rakyat yang meninjau kehidupan sungai yang tercemar karena minyak tumpah. Sekaligus “menikmati” beragam “keharuman” yang tercipta diatas permukaan sungai yang tidak lagi indah. Karena sudah tersangkut polusi pabrik pupuk, pabrik karet dan sampah masyarakat lainnya..Padahal sejak kecil aku sangat mengidam-ngidamkan untuk menjelajah sungai. Aku seakan ingin mengetahuinya sampai ceruk terdalam. Maka, ketika tiga perahu dari seberang datang ke asrama tentara sore itu, aku nyaris mati gembira. Aku tidak menyangka jika kami punya keluarga jauh yang memiliki perahu. Mereka adalah sepupu nenek. Para nenek tua berkerudung yang dikawal banyak anggota keluarga lain. Puluhan tahun tak bertemu mereka berpelukan, berciuman dan bertangis-tangisan di depan pintu. Sesaat setelah mereka menikmati teh hangat dan kue-kue yang disajikan ibu, tiba-tiba aku mendengar jika mereka datang untuk mengundang. Salah satu kerabat kami akan menikah minggu depan. Mereka berniat menjemput nenek dengan perahu itu.Dan aku, bersama sepupu-sepupuku yang seusia langsung berlari sekuat tenaga ke sungai. Disitu, aku melihat tiga perahu besar terikat di pinggir sungai. Sepupu kecil yang datang dengan perahu itu mengajak aku masuk kedalamnya. Kami bermain, tertawa dan bernyanyi bersama. Aku begitu yakin jika nenek akan ikut perahu itu, dan artinya aku pun boleh ikut serta. Wow, mengarungi sungai dengan perahu! Saking senangnya aku sampai meninggalkan sapu tanganku disitu. Saputangan bergambar mickey mouse warna merah, salah satu barang terbagus milik keluarga kami.Perlu diketahui, dikeluarga kami, segala barang yang dibeli dari gaji ayah kami adalah barang berharga yang harus terus lestari. Tidak boleh rusak, apalagi hilang. Ketentuan yang berlaku selayaknya doktrin pribadi ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dulu, aku menganggap hal ini suatu hal yang aneh dan membingungkan. Tetapi setelah dewasa aku baru paham, jika kesusahan hidup terkadang mengajarkan seseorang untuk bertindak berlebihan. Bahkan aku tidak menyangka, jika paham yang dianut keluargaku ini terkadang berdampak psikologis hingga aku dewasa. Terkadang, aku agak susah melepaskan sesuatu yang telah kubeli ke kotak sampah. Meski itu hanya sekedar bungkus permen saja.Dan kejadian kehilangan saputangan Mickey Mouse warna merah itu memang kemudian menjadi sesuatu hal yang menakutkanku. Karena sesuatu hal tersebut memang kemudian terus disesalkan ibu selama bertahun-tahun.
“Gara-gara terlalu centil, kau menghilangkan saputangan yang begitu indah. Hem, memalukan sekali! Saputangan sebagus itu dihilangkan begitu saja. Oh, tega sekali!”Bahkan, kelakuanku yang terlalu bersemangat hingga nekad mengemasi pakaian untuk ikut para sepupu jauh itu pun kerap menjadi bahan sindiran beliau sampai aku remaja. Sebab dianggap hal bodoh, karena akhirnya nenek memang tidak pergi ke acara pernikahan itu. Keluarga kami pun merasa tempat itu terlalu jauh, dan mereka juga ternyata tidak pernah merasa menyesalinya. Apalagi kemudian acara pernikahan tersebut jadi perbincangan para kerabat lain. Karena konon, banyak tamu dan keluarga yang datang di acara itu kelaparan akibat kekurangan makanan. Terlalu banyak orang yang diundang, sementara urusan konsumsi berbenturan dengan tekanan ekonomi.“Untung kau tidak ikut ke sana. Lagian ada apa dengan kau ini? Setan apa yang membuatmu seperti cacing kepanasan memaksa ingin ikut para saudara jauh yang berperahu itu?” kata ibuku saat itu.Setan apa? Apakah ada setan yang menggoda manusia untuk berjalan-jalan di sungai dengan perahu? Tetapi keinginan yang sangat kuat memang begitu menggelora diatas kepalaku. Begitu menyala sampai ingin membakar akal pikiranku. Padahal sesuatu yang pernah menyelamatkan aku di sungai itu lama kelamaan sudah seperti siluet-siluet saja dalam memoriku. Namun kerinduan akan pertemuan kembali itu seperti benar-benar memabukkanku .Dan kerinduan itu akhirnya benar-benar membakar diriku. Apalagi saat tanpa sengaja aku diberi salah seorang pejabat daerah sebuah majalah. Musi Mengalir. Majalah kebudayaan lokal. Tak ada yang aneh disana selain menceritakan tentang sejarah Sriwijaya, songket sampai peninggalan prasejarah. Tetapi ada yang membuat aku tercabik dibuatnya. Salah satu artikel tentang Antu Banyu yang melegenda. Seakan ceruk terdalam dihatiku menggelegak dan mengeluarkan larva. Akhirnya, aku memang terbentur dengan CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali). Aku harus mencarinya! Benar-benar mencarinya.Aku kembali ke Jakarta. Aku menghimpun kekuatan untuk mengupas tuntas permasalahan ini. Aku tidak mau timbul korban lagi. Aku harus mencari cara untuk membuka tabir misteri ini. Sudah begitu lama misteri itu terdiam di dasar terdalam sungai. Tanpa ada orang yang mau melirik, apalagi mengusik. Kuatnya mitos yang menyelimutinya membuat misteri itu seperti tidak menarik bagi segala jenis ilmuwan atau tenaga ahli kebinatangan yang mengurusi masalah itu. Seperti tidak ada niat sama sekali untuk menambah daftar spesies baru di dunia ini.
Hal tersebut bahkan sempat terungkap oleh teman-temanku di Palembang, yang ternyata ada cukup minat untuk mengomentari urusan Antu Banyu ini.“Padahal jika pemerintah daerah serius mengurusi misteri Antu Banyu ini, bukan tidak mungkin justru akan mendatangkan keuntungan dari meningkatnya jumlah kunjungan wisata?”
“Eh, kalau produser film Hollywood tahu soal ini, bukan tidak mungkin filmnya jauh lebih dahsyat dari Anaconda, The Lost World atau apalah yang sejenis itu”
“Yang jelas, dunia akan gempar menatap sosok Antu Banyu yang sebenarnya”Tetapi lagi-lagi itu hanya diskusi, dan diskusi saja. Tidak ada tindak lanjut. Dan memang seakan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Sebab yang menggelar percakapan bukan berasal dari tenaga ahli biologi, tim pemburu hantu atau pun pendobrak misteri. Yang berkumpul ini, hanya sekelompok orang-orang yang hanya kebetulan “tertarik” dengan Antu Banyu ini. Hanya tertarik. Tidak mencoba untuk melirik, apalagi mengulik.Bertahun-tahun, aku berharap, dapat bertemu dengan salah satu pihak yang dapat membuka jalan pertemuanku dengan sosok misteri di masa lalu. Tetapi siapa dan bagaimana? Bercerita tentang sosok itu saja aku seperti tidak memiliki kekuatan. Aku akan ikut berbicara, kalau ada orang yang lebih dulu mau berbicara.
Sampai akhirnya, aku bertemu dengan orang-orang yang membuatku bukan hanya mampu berbicara.2008
Kami memutuskan bertemu di salah satu kafe di bilangan Sudirman. Siang itu cuaca demikian buruk. Bukan hanya hujan deras mengalir, tetapi juga karena hantaman petir. Aku bahkan memiliki firasat yang jauh lebih buruk atas perkembangan pertemuan tersebut. Terkadang aku menyesal mengapa aku telah dengan iseng menulis semaunya di blog pribadi. Apa aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada banyak orang yang tertarik? Dan orang-orang itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang kuharapkan untuk tertarik? Tapi aku telah menulis tentang itu hampir setengah tahun lalu. Dan memang ada banyak pesan elektronik yang kuterima sejak itu, meminta penjelasan lengkap tentang tulisan itu. Mereka ingin aku menulis lebih banyak lagi. Bahkan ada banyak orang juga yang menantikan pertemuan denganku, berharap bisa memuaskan rasa penasaran mereka. Begitu dahsyatkan tulisanku itu?Dan kemudian, aku memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan empat orang, yang kuanggap betul-betul punya keseriusan untuk membicarakan tentang Antu Banyu. Mereka, seorang penulis novel picisan yang berharap bisa menghasilkan karya sastra terhebat zaman ini, sarjana pengangguran yang sudah capek cari kerja, mantan pecandu narkoba yang ditolak kembali ke rumah dan cewek narsis yang bermimpi jadi artis.Aku menatap mereka satu per satu. Tuhan, aku menghela nafas. Jelas-jelas mereka bukan pasukan yang dapat diandalkan. Aku pahami itu jauh sebelum mereka dengan penuh perasaan mencoba saling memperkenalkan diri.
“Andra, panggil aku begitu. Aku ingin membuat karya baru spektakuler. Mungkin dapat kuilhami dari Antu Banyu ini. Ya, aku memang telah menelurkan beberapa novel hebat sebelumnya. ”
“Apa saja itu?” kami berebutan ingin tahu.
“Cinta Usang, Bukit Indah Cintaku, Tertambat Cinta di Sekolah…”
“Belum pernah dengar itu….”“Yah, karyaku memang hanya dinikmati kalangan tertentu. Tidak sembarangan memang”
Pria berusia diatas tiga puluh tahun itu nampak begitu percaya diri. Tubuhnya kurus ceking bak lidi. Rambut gondrong sebahu yang dikucir ala pendekar zaman dulu. Jaket dan celana jinsnya tampak awut-awutan dan sikapnya sok cuek dan sinis banget. Tetapi bukan sikap sinisnya itu yang bikin mual dihati. Gayanya bersikap yang sok ingin dimengerti dan dipahami sebagai seniman sejati. Sok paling aneh, paling hebat, paling pintar, paling memahami banyak hal dan paling-paling lainnya.Mungkin ini salah satu contoh orang yang berharap ingin sekali diyakini sebagai seorang seniman. Banyak orang berpendapat seniman itu gaya hidupnya sebegitu berantakan, karena imajinasinya sering melompati daya pikir orang kebanyakan. Padahal tidak setiap seniman begitu. Kalau perilakunya mungkin agak “lain” dari orang kebiasaan, itu mungkin. Tetapi untuk memaksakan diri dianggap seniman dengan membentuk karakter nyeleneh demi suatu pengakuan juga menyedihkan. Seperti laki-laki itu, yang bertingkah mirip orang yang tersesat di ibu kota, abis kecopetan, lalu terpaksa menginap di terminal berbulan-bulan lamanya. Dan aku yakin, orang ini sebenarnya sudah putus asa karena tidak pernah mampu melahirkan karya-karya yang sanggup dikenang mungkin bahkan oleh segilintir orang saja.Lalu kemudian, aku melihat pemuda bertubuh tinggi besar dengan muka putih pucat, bagai penat menahan beban berat. Dia mengaku sarjana ekonomi dari universitas swasta terkemuka di Jakarta. Tetapi gayanya lebih mirip anak orang kaya yang sedang digencet uang jajannya. Akhirnya itu terbukti juga dari cerita hidupnya yang diungkap panjang lebar segala.
“Namaku Jeff. Cari kerja di Jakarta ini susah. Semua butuh pengalaman, keuangan dan segala bentuk dukungan. Usaha bapakku bangkrut pas aku selesai di wisuda. Ibuku ribut dengan bapakku dan minta cerai segala. Bapakku juga sekarang di penjara karena memukul pria selingkuhan ibuku. Adik-adikku sih masih kecil, sehingga bisa jadi tanggungan paman dan bibiku yang cukup kaya. Tapi mereka kan tidak mau menampung bujangan usia 25 tahun. Tapi ya, itu. Cari kerja tanpa koneksi dan lain-lainnya itu susah. Aku kan tidak mau jadi cleaning service atau pelayan kafe? Nanti bisa diketawain teman-temanku. Mending aku berpetualang aja. Mampus-mampus gua!”Setelah itu mata kami mengarah pada sosok yang tidak kalah menyedihkannya. Namanya Aga. Tubuhnya kering kerontang bak habis kehilangan banyak darah. Matanya sayu, sangat layu. Sehingga aku berkeyakinan jika pemuda yang satu ini sebenarnya memang sangat berharap cepat mati. Tetapi yang pasti, dia tidak ingin mati bunuh diri.“Aku bersumpah tidak lagi mengenal barang haram itu. Tetapi tak ada satu pun penghuni rumahku yang percaya. Mereka lebih senang kehilangan anak, kakak atau adik mereka. Ya, mereka menganggap aku tidak lebih buruk dari sampah. Cuma mengotori saja. Sebab itu aku ingin mencari suatu petualangan seru yang akhirnya dapat membuat aku kehilangan kesempatan hidup lebih lama”“Kamu pikir, kita semua ini akan menuju ke kematian?” tanyaku ketus.
“Tulisanmu kan tentang Antu Banyu yang telah mencabut nyawa beberapa orang?”
“Eh, aku tidak pernah menuduh Antu Banyu telah membunuh sekian banyak orang ya? Aku cuma penasaran dengan sosok ini, dan setidaknya dia suspect sementara untuk beragam kejadian yang membingungkan”
“Apa bedanya?”
“Maksudmu?”
“Anggap saja proyek kita ini memang memancing ke kematian”
Proyek? Aku memukul jidatku. Tapi belum hilang peningku, terdengar suara lain. Suara serak-serak yang dibuat mendesah dan bersengau. Mirip penyanyi lokal yang habis-habisan meniru karakter gaya suara penyanyi luar biar dianggap ‘berkarakter”.“Kalau aku sih setuju jika hal ini tidak akan mengarah ke kematian. Aduh, jangan serem-serem dong. Aku ikut ini, karena aku sedang break syuting film dan iklan. Ya, sekedar warming up-lah! Hitung-hitung refreshing. Siapa tau, kalau memang kita berhasil mengungkap misteri ini kepada dunia, terus nanti ada produser yang memfilmkan, aku kan bisa terlibat jadi salah satu tokoh utamanya. Ya…kan?”Mata kami kemudian tertuju pada wanita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia memang berupaya sekali untuk dianggap sebagai salah satu pelengkap dunia hiburan tanah air. Mukanya sih tidak cantik-cantik sekali, tetapi harus diakui, dia memang punya body yang sejajar dengan penyanyi dangdut heboh abad ini. Rosemary, itu nama kerennya. Tetapi di KTP-nya, ternyata Rosmaryamah.Tuhan. Aku menggeleng-gelengkan kepala berkali-kali. Benarkah aku akan mengungkap misteri Antu Banyu ini dengan manusia-manusia aneh ini? Apakah aku berpikir bahwa mengorbankan mereka pun tak akan membuat aku begitu sedih? O, lihatlah manusia-manusia tanpa arah ini. Sebagian pemimpi yang sial, sementara sebagian lagi orang yang telah sial karena kehilangan mimpi. Jika mereka hilang pun di muka bumi, kurasa tidak ada orang yang mau menangisi. Tetapi tegakah aku mengorbankan mereka-mereka yang nasibnya tidak begitu mujur ini demi rasa kerinduanku akan Antu Banyu? Apa aku sendiri lupa jika sudah banyak orang-orang yang ada disekelilingku pelan-pelan kehilangan kesempatan untuk menikmati dunia? Tiba-tiba aku merasa pusing.2003
“Bangun! Bangun, dek. Bangun!”
Di pagi buta itu, suara kakak keduaku menohok tajam. Mendepak mimpi-mimpi indah yang belum sempat kesampaian.
“Ada apa sih?”
“Kau harus nonton tivi!”
“Apa?”
“Cepatlah! Kau tidak akan pernah membayangkan bisa menonton ini secara langsung”Berlarian kami menerjang pintu berebut menuju ruang tamu. Meski rasa kantukku masih lembek bergayut dimataku, tetapi jantungku seakan berpacu untuk menguak rasa penasaran itu. Sungguh bukan suatu kebiasaan kakakku menyeretku untuk nonton tivi di tengah suasana pagi yang mestinya masih tetap ramah dengan selimut ini. Pastilah ada suatu kejadian mahadahsyat di tivi yang melibatkan orang-orang sekeliling kami. Tetapi ketika mukaku sudah sekitar setengah meter di depan tivi, aku malah terbengong-bengong sendiri. Sebuah gedung bertingkat nampak dilalap api. Aku merasa tidak akrab dengan gedung yang satu ini. Itu bukan rumah saudara, tetangga atau milik orang-orang yang kukenal selama ini.
“Gedung apa ini?”
“Karaoke Party”
“Lalu? Kakak membangunkan aku pagi-pagi untuk melihat ada tempat karaoke…” mendadak nafasku nyangkut dikerongkongan. Oh, Tuhan! Mendadak aku ingat sesuatu.Dia yang sering pulang tengah malam dengan seragam pegawai karaoke. Jika aku pulang kerja kemalaman, kami sering berjalan beriringan. Kemudian kami berpisah, karena dia harus terus melanjutkan perjalanan di tikungan tergelap yang penuh rumput liar dan pohon-pohon pisang tinggi besar. Dia begitu berani menjalani kehidupan malam yang begitu keras demi membantu kebangkitan ekonomi keluarga semenjak ayahnya memutuskan menjalani kehidupan dengan beristri dua. Persahabatan kami yang pernah terjalin sewaktu masih belia, membuat ikatan yang begitu kuat meski kami jarang bersua. Aku ingat senyumnya yang begitu ramah, selalu terlihat indah jika kami kembali bertemu di malam-malam yang gelap itu. Dia yang pernah menyelamatkan hidupku, menarik aku dari sungai itu bertahun-tahun yang lalu.
“Ya, dek. Vina kerja di karaoke itu” terdengar suara kakakku. Sungguh, aku tidak ingin terjadi sesuatu hal buruk padanya.Tetapi air mata itu tidak dapat kubendung lagi, ketika kudengar berita tentang ratusan korban kebakaran gedung karaoke itu. Bukan dari tivi, radio atau koran lagi. Karena siang itu ibuku buru-buru membawa sebaskom beras, berlari-lari dengan kerudung rapat di kepala. Aku tidak sanggup mengikuti ibuku. Aku lebih suka di rumah, menangis sepuasnya. Lebih baik aku tidak melihat jasadnya meski untuk yang terakhir kalinya. Karena kudengar banyak tetangga yang sudah melihatnya, menceritakan hal itu begitu terbukanya.
“Seluruh tubuhnya terbakar. Kulitnya sebagian gosong, sebagian mengelupas….”
“Betapa tersiksanya dia dalam kondisi itu”Dan aku hanya menutup rapat kupingku dari berita mulut tetangga itu. Mereka itu kelompok ibu-ibu penggosip di warung atau di rumah tetangga. Mereka menganut gaya hidup hiperbola, baik dari segi bahasa maupun tingkah lakunya. Aku memilih menunggu berita dari ibu. Mungkin tidak begitu buruk kedengarannya, tetapi tetap saja membuat hatiku berdarah-darah.Kata ibu, Vina sudah mempersiapkan rencana pesta pernikahannya yang akan di gelar beberapa minggu lagi. Kekasihnya sudah berulang kali memintanya berhenti bekerja dari karaoke itu. Tetapi Vina selalu ingin membantu keuangan keluarganya. Saat api tengah berkobar, kekasih yang menjemputnya memintanya meloncat dari tangga. Tetapi dia takut dengan ketinggian dan kobaran api. Vina malah berlari ke lantai lain dari gedung itu, berharap menemukan jalan keluar. Malang, petugas pemadam kebakaran menemukannya pingsan di tengah lautan asap dengan tubuh terbakar api.Dalam perjalanan menuju rumah sakit, menurut sang kekasih, Vina sempat tersadar. Berulang kali dia mengatakan kalimat yang sangat mengharukan. “Kak, aku sudah tidak kuat” demikian kata kekasihnya yang diceritakan kepada ibu. Suatu kalimat yang tidak kutemukan dari semangat hidup seorang Vina yang kukenal sejak kecil dulu. Biar hidup susah, Vina begitu semangat bersekolah. Saat dia sakit pun dia tetap pergi ke sekolah. Suatu kali menurut ibuku, Vina pernah berlari ke rumah kami yang sudah pindah cukup jauh dari rumahnya. Listrik di asrama tentara sedang mati. Vina ke rumah kami untuk minta izin menumpang menyetrika baju seragamnya. Biar seragamnya lusuh, Vina selalu ingin tetap terlihat rapi jika menuju sekolah.
Bekerja pun Vina semangat luar biasa. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan dengan ijazah sekolah menengah zaman ini. Jika kemudian hanya usaha karaoke yang menghargai kecantikan dan keluguannya untuk menjadi pelayan jasa pemutar lagu bagi para pengguna karaoke, dia pun tetap semangat. Meski hampir seluruh tetangga mencibir dan mencurigai pekerjaan yang membuatnya harus terpaksa selalu pulang tengah malam itu. Tetapi Vina tetap kuat dengan pilihannya.“Ada kesempatan bekerja. Aku bekerja. Aku lebih kuat mendengar ocehan para tetangga itu, dari pada melihat ibu dan adik-adikku kelaparan. Mereka itu bisanya cuma ngomong aja. Jika aku tidak bekerja, apa mereka itu yang akan memberi kami makan?” katanya, ketika kami sama-sama pulang bekerja di tengah malam itu.Lalu Vina juga menguntai cerita tentang harapannya dengan sang kekasih yang ditemuinya saat bekerja di karaoke itu. Seorang lelaki baik yang mau menerima dirinya apa adanya. Termasuk berjanji untuk membantu kehidupan keluarga Vina.
Dan aku juga masih ingat ucapannya waktu itu,“Aku yakin, semua kesulitan ini suatu saat pasti akan berakhir”Memang semuanya kini telah berakhir. Vina sudah tidak lagi merasakan beratnya himpitan hidup. Dia sudah tidak perlu lagi bertanggung jawab penuh atas tuntutan perut seluruh anggota keluarganya. Meski dia sudah lama meninggal pun, ketika kemudian aku masih sempat tidur di kamarku yang tepat di pinggir jalan itu, terkadang saat tengah malam aku masih seperti mendengar langkah kakinya. Ketukan hak sepatunya yang tegap berjalan menuju ke rumahnya. Atau terkadang juga sayup-sayup aku mendengar senandungnya, menyanyikan lagu-lagu yang sering di putar di tempatnya bekerja. Suatu hal yang membuat aku sering menitikkan air mata.Sepeninggal Vina, kondisi keluarga Vina semakin memburuk. Ayahnya meninggal, dan sebagian harta sang ayah justru jatuh ke tangan istri mudanya. Adiknya yang bungsu, Eve, terpaksa menikah muda, tetapi kehidupannya justru tidak lebih baik. Ibunya yang kudengar terakhir kali malah jadi pembantu rumah tangga karena harus membiayai hidup adik laki-laki Vina yang terganggu jiwanya. Adiknya Vina, Elang, sudah lama jadi kurang waras. Saat kecil, dia sempat ikut kakeknya ke Jakarta. Elang pernah bercerita pada kakakku kalau di kota ini dia justru diperbudak sang kakek dan nenek tirinya. Jadi sapi perah, mesin uang, atau sejenisnya. Dia bekerja membanting tulang jadi pedagang asongan cilik. Entah jualan Koran, makanan, atau mainan. Elang sangat rindu ingin kembali ke rumah, tetapi sang kakek tidak pernah mengizinkannya. Bukan sekali dua kali dia ingin kabur, tetapi sang kakek selalu menemukannya dan menghajarnya.Kesempatan kabur itu datang setelah dia lulus SMA. Dengan semangat membara dia pulang ke kampung halaman. Tetapi malangnya, dalam perjalanan pulang dia di rampok. Ijazah SMA Elang hilang digondol rampok tak berperikemanusiaan itu. Hal ini yang menurut Elang membuat dia stres karena tidak bisa mencari pekerjaan. Akhirnya Elang hanya mendapat pekerjaan menjadi kernet bus kota. Lagi-lagi, dia mendapat musibah. Saat bergelantungan di bus kota mencari penumpang, dia terjatuh dan kepalanya membentur trotoar jalan. Dia memang lama dirawat di rumah sakit. Tetapi setelah sembuh, jiwanya sudah menjadi terganggu. Tingkah lakunya tidak seperti orang normal. Tidur di sembarang tempat, bicara dan tertawa sendiri, senang berlari atau malah menangis tiada henti.Pada awalnya aku mendengar, Elang gila karena pernah mempelajari ilmu-ilmu mistis. Tetapi setelah mendengar cerita kakakku, aku kemudian berpikir logis. Elang sudah didera masalah psikologis sejak kecil. Kerampokan ijazah dan jatuh dari bus kota itu pelengkap penderitaannya. Hanya saja, setelah kematian Vina, aku merasa perlu mengungkap kejadian yang sebenarnya. Mengapa Vina harus mati dalam keadaan mengenaskan? Bukan karena sakit atau katakanlah, kematian yang wajarlah. Apa dia pernah menceritakan tentang peristiwa kami di sungai dulu itu dengan seseorang? Lalu siapa orang itu? Apakah Elang? Kalau itu benar, maka mungkin saja Elang jadi gila. Kemudian Vina menjemput ajalnya karena telah membongkar peristiwa itu.
Tapi, rupanya analisaku salah. Bertahun kemudian, Eve, mengaku bahwa dialah yang telah menceritakan soal Antu Banyu kepada kakaknya.“Waktu itu kak Elang sedang sibuk mendalami ilmu-ilmu mistis. Katanya dia sering melihat mahluk gaib. Aku ingat kejadian kita di sungai dulu itu. Kuceritakan padanya, agar kakakku bisa mencari mahluk itu” kata Eve, yang kutemui sambil menggendong anaknya.
“Kamu kan pernah kuperingatkan dulu agar tidak cerita”
“Memang kenapa?”
“Nanti kau kena musibah. Juga orang yang mengetahui ceritamu itu”
“Lalu, Usie mati itu juga karena Vina cerita soal Antu Banyu itu padanya?”
“Apa?”Oh, aku ingat tentang Usie. Saat aku kelas dua SMA, Usie mengalami kecelakaan tragis. Bus mahasiswa yang dinaikinya terbalik. Belasan mahasiswa luka-luka. Tetapi anehnya, Cuma Usie yang kehilangan kepala. Dia duduk tepat di pinggir jendela. Kaca jendela bus tersebut ternyata begitu tajam menggores lehernya. Ibu dan kakakku waktu itu juga sempat menghadiri prosesi pemakamannya. Mungkin hal itu cukup mengguncang perasaan mereka. Sehingga membuat aku kemudian tidak diperbolehkan memilih kuliah di kampus Usie yang jauh itu. Keluargaku takut aku juga mengalami kecelakaan yang sama seperti Usie.Eve menjelaskan, jika Vina dan Usie cukup berteman akrab. Dapat dimaklumi, karena ayah Usie merupakan dokter yang kerap menjadi langganan keluarga di lingkungan kami. Ibu Vina yang sering sakit-sakitan merupakan pasien tetap ayah Usie. Vina kerap mengantar ibunya berobat ke rumah sang dokter. Kunjungan ini sering membuat Vina dan Usie bertemu. Apalagi mereka memang pernah satu sekolah waktu masih SD dulu.“Kata Vina, anak tetangga Usie hilang saat berenang di sungai. Lalu Vina cerita soal peristiwa kita di sungai itu. Vina itu bukan tipe orang yang suka menceritakan banyak hal. Aku yakin itu kebetulan saja, karena kondisinya pas. Pas ada anak hilang dicaplok Antu Banyu” ungkap Eve.
“Dan kita sudah mengetahui penyebab kematian Usie sekarang” bisikku.
“Jadi, kakakku si Elang juga gila karena aku cerita soal peristiwa di sungai itu?”
“Mungkin”Ya, mungkin saja. Lalu kenapa Elang tidak mati setelah mendengar cerita itu? Kenapa Elang hanya terganggu jiwa, sama seperti halnya Doddy? Doddy dan Eve, pasangan “pengantin” kecil kami itu. Dan Eve, dia yang memberitahukan kisah itu kepada Elang. Toh, dia sendiri tidak mati. Apa karena Eve dan Doddy saat itu memang tidak sempat melihat “mahluk” yang telah menarikku itu dari dasar sungai?Aku mulai merentang kisah tragis yang telah terjadi. Teman sekolah kakak Jamie yang tewas kecelakaan. Kata Tantry, dia sempat ngobrol soal sungai dengan Jamie. Anggaplah Jamie bercerita pada bocah malang itu. Lalu, Jamie sendiri mati. Konon, ditangan ayahnya yang kalap melihat anak itu tiba-tiba berulah seperti setan. Lalu ada perubahan dari sosok Doddy. Anak itu perlahan menjadi berubah aneh. Seakan memiliki dunia sendiri diatas dunia yang sebenarnya. Sampai dewasa dia akhirnya tumbuh menjadi sosok yang menakutkan bagi banyak orang. Kemudian aku juga mendengar kabar, jika Budi saat menjelang remaja juga tewas akibat kecelakaan di jalan raya. Lalu ada Elang, adik Vina dan kakak Eve yang juga terganggu jiwanya. Menyusul kematian Vina yang tak kalah tragis. Sementara sebelumnya nasib Usie, lebih menakutkan lagi.Setelah peristiwa di sungai itu, siapa yang belum mati? Aku. Ya, tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin aku dapat menulis cerita ini. Lalu, Doddy dan Eve. Kenapa (lagi) Doddy hanya terlihat agak gila dan Eve biar pun hidupnya banyak masalah tetapi tampaknya baik-baik saja.
“Aku memang tidak melihat apa pun saat itu. Seingat aku, aku cuma terlalu ketakutan. Kemudian menangis. Lalu tiba-tiba kau sudah berbaring di pinggir sungai dalam pelukan Vina. Kurasa Doddy pun tidak melihat apa-apa. Dia sibuk mendiamkan aku agar tidak terus menjerit-jerit. Kenapa sih kau merasa urusan Antu Banyu ini penting banget? Kalau memang masalah semua ini memang benar karena Antu Banyu, maka ini tentu bukan salah kami. Kaulah yang nekad berenang di sungai itu. Sudah tahu kau tidak bisa berenang. Kau yang bertemu sosok itu, dan kami yang terpaksa menaggung akibatnya. Apa kau pikir, aku juga akan mati dengan cara yang begitu parah atau ikutan jadi gila?”Itulah kalimat pamungkas Eve, saat terakhir kali aku menemuinya. Begitu dahsyat menjagal perasaanku. Eve benar. Akulah yang bersalah. Aku yang membuat begitu banyak nyawa mati sia-sia, juga mengungkung banyak jiwa ke dunia hayalnya. Aku harus menghabisi kisah memilukan ini. Dan keinginan itu begitu kuat, ketika kakakku Lizbeth tiba-tiba juga kehilangan makna hidup. Kelakuan lebih buruk dari Doddy, bahkan tak jauh berbeda seperti Elang. Ketiganya kemudian jadi lajang yang mengalami krisis kejiwaan. Kesepian, dijauhi banyak orang.
“Aku membaca buku diarymu. Wah, ternyata kau menyimpan banyak rahasia ya?”
Itu ucapan Lizbeth terakhir, sebelum dia terjebak dalam dunia maya. Kembali, hal tolol kulakukan. Diary yang kutulis saat aku duduk di kelas dua SMP itu memang sempat menuliskan kisah hidupku di masa kecil. Termasuk, tentang peristiwa di sungai itu. Aku tidak tahu jika akhirnya hal itu justru mengguncang jiwa kakak perempuanku sendiri.Lalu ayahku? Kenapa beliau bisa jatuh dari rumah yang waktu itu sedang kami bangun sehingga tangan kanannya patah? Apa karena ayah telah membuka kisah “pertemuannya” dengan Antu Banyu pada ibu, lalu tanpa sengaja ibu menceritakan hal itu kepadaku?Ya, aku ingat. Sore itu, saat aku sedang asyik bermain, tiba-tiba aku melihat begitu banyak orang berlari ketakutan. Jelas, aku tidak tahu siapa orang yang sedang dibopong beramai-ramai itu. Tapi telingaku mendengar jelas orang memanggil-manggil nama ayahku dengan histeris.
“Ayah, ayah kenapa?” tanyaku pada ayah yang tergeletak tak berdaya di ruang tamu. Begitu banyak orang yang mengurumuninya. Ibu dan kakakku sudah pada menangis semua. Tapi tak ada yang menjelaskan kepadaku. Ayah sendiri tampak tidak bersedia menunjukkan rasa sakitnya. Beliau hanya berusaha terlihat baik-baik saja dengan senyumnya.Dan setelah mobil tentara itu membawa ayah ke rumah sakit, aku baru tahu kejadiannya. Ayah yang membangun rumah impian kami itu, tiba-tiba jatuh dari atas rumah yang dibangun dengan tangannya sendiri itu. Tubuh ayah menghantam tanah bakal lantai rumah kami. Malangnya saat jatuh, tangan kanan ayah tertekuk sehingga patah. Karena memang bekerja sendiri dan lokasi kejadian memang sepi, membuat ayah nyaris terlambat mendapat pertolongan. Beruntung, ada Oom Simatupang, salah satu tentara yang sedang menggiring bebek peliharaannya. Berkat Oom Tupang ini, ayah bisa diselamatkan.Musibah yang dialami ayah, membuatnya harus lama berada di rumah sakit. Proses pembangunan rumah kami pun akhirnya tersendat. Tetapi setelah ayah sembuh, meski tangannya kemudian menjadi cacat (menjadi agak bengkok), rumah kami pun dibangun kembali. Ada banyak hikmah dari kejadian ini. Sebab sejak kecelakaan yang menimpa ayah, orang jadi banyak tahu jika ayah nekad membangun rumah kami itu sendiri. Tanpa bantuan tukang bangunan satu pun. Perjuangan ayah ini akhirnya menarik simpati banyak pihak. Karena akhirnya, tidak sedikit orang yang membantu ayah untuk membangun rumah tersebut. Selain Oom Tupang, ada juga beberapa tentara lain. Salah satunya seorang tentara muda yang tampan.
Aku lupa nama tentara berpangkat prajurit dua ini. Tetapi aku ingat, suatu sore dia datang mengunjungi ayah. “Biar saya nanti membantu bapak membangun rumah ini. Saya ikhlas pak menolong. Saya tidak tega melihat bapak membangun rumah dengan tangan yang masih sakit seperti itu”Aku memperhatikan tentara tersebut. Sambil bicara, dia sibuk mematah-matahkan dahan kecil rapuh. Duduk diatas kertas bekas semen sambil menghadap ayah. Dan besok sorenya dia benar-benar datang lagi. Begitu juga sore-sore selanjutnya. Dia membantu ayah mengaduk semen, mengangkat batu atau kayu. Begitu bersemangat. Lama-lama dia seakan menjadi bagian dari keluarga kami. Sebab dia membantu kami membangun rumah impian itu. Kami sangat menghormati dan menyayanginya. Ibu bahkan selalu membuatkan kue-kue yang paling enak untuknya. Kue-kue yang dinikmatinya dengan begitu lahap.Jujur, aku sangat senang memperhatikan tentara yang satu ini sedang makan. Mungkin, karena waktu itu aku masih terlalu kecil sehingga masih suka tertarik dengan hal-hal unik dan baru disekitarku. Tapi gara-gara hobiku memperhatikannya, aku malah sempat mendapat malu besar. Saat bolak-bolak mengintipnya lagi makan, tiba-tiba aku terpeleset dan masuk ke kubangan air bekas hujan. Untung aku masih kecil saat itu. Sehingga tingkah laku dimaafkan banyak orang. Tetapi tentu saja aku malu sekali. Dan sejak itu, aku memang tidak pernah mengintip tentara itu makan lagi. Sampai kemudian rumah kami akhirnya cukup pantas untuk ditempati. Kebetulan, tentara muda itu juga pindah tugas. Sayang, kami tidak sempat banyak berterima kasih. Tetapi aku tahu, Tuhan akan memberikan rezeki lebih pada pemuda baik hati ini. Yang begitu ikhlas menolong seorang tentara bertangan cacat yang sedang membangun rumah.Ya, begitulah banyak peristiwa aneh yang terjadi. Kecelakaan, kematian, kekurang warasan dan apa pun itu yang membuatku bergidik ngeri. Apa karena mereka tanpa sengaja membocorkan rahasia tentang si Antu Banyu ini? Apakah ini tidak terasa berlebihan? Rasanya sulit diterima akal. Siapa sebenarnya Antu Banyu ini? Mereka tentu bukan Tuhan. Tetapi apakah mereka dari kelompok iblis atau setan?Lalu, kenapa orang-orang yang tertarik dengan tulisan di blog-ku itu tidak jadi gila? Atau katakanlah tidak tertimpa kecelakaan atau langsung tiba-tiba mati misalnya. Kenapa? Apa memang mereka ini memang ditakdirkan untuk membantuku membuka tabir misteri ini? Karena memang akulah yang membuat musibah beruntun ini datang, dan mungkin akulah yang harus menyelesaikannya. Apa memang aku harus mati bersama orang-orang ini? Entahlah. Tapi, haruskah ada banyak korban lagi?Yang jelas, akhirnya aku menghimpun kekuatan menguatkan tekad mengunjungi kembali sungai Musi. Bersama orang-orang aneh itu. Beserta tambahan, dua orang bule asal Amerika. Jans dan Bryant. Mereka ini adalah kenalan Rosemary dari bar tempat biasa cewek ini nongkrong dengan para calon artis lainnya.. Jans dan Bryant hanya pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan karena dampak krisis global. Perusahaan tempat mereka bekerja gulung tikar dan mereka lalu mendapat sedikit uang pesangon sekedar terima kasih karena pernah mengabdi selama beberapa tahun. Stres tidak mendapat kerja baru, mereka lalu berpetualang ke Indonesia. Jika kemudian mereka berlagak jadi hippies, itu setelah dana dikantung mereka sudah menipis. Sementara mereka masih berharap dapat menikmati wisata murah sampai masa kunjungan mereka habis. Akhirnya, melalui rekomendasi Rosemary, keduanya memang nekad ikut.
Saat itu kami sepakat mengumpulkan uang untuk biaya perjalanan dan penginapan kami di Palembang nanti. Aku memang tidak akan membiarkan mereka menginap di salah satu rumah keluargaku. Aku justru tidak ingin jika “proyek” misterius ini diketahui oleh orang-orang terdekat. Biarlah begitu. Jika banyak orang bertanya, maka kukatakan saja jika kami sedang mengawal dua orang turis mancanegara.Siang itu kami sudah berada di Palembang. Bandaranya yang berstandar internasional memang cukup memenangkan urat syaraf. Tetapi itu hanya sebentar. Kita akhirnya kami memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel kelas melati, maka pertengkaran diantara kami nyaris tidak terelakkan lagi. Sebagian ingin tinggal di hotel yang kondisinya jauh lebih murah lagi, sebagian justru merasa urusan dana tidak perlu dipikirkan sampai sedemikian itu. Inilah susahnya melakukan petualangan dengan orang-orang yang ingin cepat mati, tetapi tidak mau mati dalam keadaan tidak pegang uang. Namun akhirnya situasi itu dapat berganti. Kami akhirnya menyewa tiga kamar. Satu buat aku dan Rosemary, dua kamar lagi diperebutkan para pria; Andra, Jeff, Aga, Jans dan Bryant.Malam pertama mengenal sungai Musi, kami habiskan memang benar-benar di pinggir sungai itu. Tepatnya di lokasi Benteng Kuto Besak (BKB), yang dulunya merupakan lokasi pasar buah nan becek, rawan dan bau banget. Pemkot setempat telah menyulapnya menjadi lokasi wisata yang sekarang malah jadi pusat kegiatan seni. Beberapa konser artis top ibukota rutin dijalankan. Bahkan launching Visit Musi nan megah bersama beberapa menteri tahun 2008 lalu juga di gelar disana. Meski belum terdengar jelas berapa volume terakhir serapan jumlah turis.
Bagiku, kota ini bukan hanya sekedar kota kelahiran, dan juga kota dimana aku bertahun-tahun melewati masa remajaku. Meski kota ini seperti “malas” untuk membangun kembali kejayaan kebudayaan, tetapi kemajuannya memang cukup luar biasa. Bayangkan, dalam hitungan tahun kota ini sudah padat dengan Mall. Fly over dibangun, jalan-jalan diasah, hotel-hotel berbintang menjamur. Jika dulu Palembang cuma punya sebuah jembatan besar, tetapi kini, banyak hal-hal besar lain yang dapat dikagumi dan diperbincangkan.Tetapi itulah, jika aku boleh mengkritik kotaku sendiri, pasti terdapat kekurangan. Sebenarnya kota ini sanggup mendatangkan turis jauh lebih besar, bahkan (mungkin) dari beberapa kota lain sejenisnya (yang juga tua dan kuat unsur melayunya). Palembang kental dengan riwayat indah Sriwijaya. Tetapi gaung keemasan di masa lampau itu, ibarat hanya sekedar cerita lama. Tidak ada suatu bentuk penguatan disana-sini untuk memanfaatkan kenangan sejarah tersebut. Kalau soal promosi wisata, entahlah, ini jargon politik atau sekedar proyek pelepasan dana. Yang jelas, hanya berupa kegiatan-kegiatan resmi pemerintah yang minim realisasi.Contohnya lokasi BKB ini. Mestinya, lokasi ini dilengkapi sarana dan prasana ala lokasi wisata pada umumnya. Tetapi yang terlihat, justru hanya beberapa pedagang kaki lima yang berjualan santai untuk kebutuhan biasa. Seperti makanan atau minuman. Belum tampak ada barisan pedagang kecil yang menggelar souvenir unik khas daerah. Memang sesekali tempat ini juga jadi ajang bazar murah untuk kegiatan menyambut hari raya, misalnya. Dimana banyak pedagang pakaian, perhiasan dan mainan menumpuk disitu menjalankan perputaran uang. Jadi memang, teriakan untuk mendatangkan turis, tidak sepadan dengan daya juang tingkat akhir yang justru sebenarnya dapat meningkatkan perekonomian dalam jumlah besar.Kami akhirnya malam itu makan di restoran terapung. Suasana memang sangat indah di waktu malam. Lampu-lampu yang menaburi jembatan Ampera, membuat kita ibarat sedang liburan di dekat jembatan San Fransisco (ehem!). Restoran terapung ini memang salah satu bentuk upaya memancing wisatawan. Suatu ide unik yang mestinya terus didukung dan mengalami perkembangan. Sungai Musi di waktu siang, dapat terlihat berwarna coklat keabu-abuan. Puluhan kapal kecil hilir mudik, sementara kapal besar nampak manis bersandar. Kudengar, dipinggir sungai ini nanti, akan dibangun sebuah hotel besar. Bersandingan dengan rumah-rumah penduduk yang rapat menjilat air sungai.Dipinggir sungai Musi, masih terdapat kebudayaan Palembang. Mereka umumnya keturunan warga asli yang berbicara seperti layaknya orang Jerman, alias tidak mengenal lafal baik huruf R. Tetapi nasib orang Palembang asli yang tinggal di pinggiran, tidak ada ubahnya dengan kenyataan keseharian. Mereka terpinggir dengan segenap kebudayaan, kematangan ekonomi dan serbuan semangat kaum pendatang.Di kota ini, sudah jarang terlihat para rutin wanita menenun songket. Kain indah berbenang emas. Suatu kegiatan, yang dulu sangat dikagumi kaum penjajah. Saat duduk di kelas dua SMP, aku pernah satu kelas dengan teman yang bisa menenun songket. Dan selama aku sekolah di kota ini, memang hanya satu teman itulah yang pernah kutemui memiliki keahlian tersebut. Banyak temanku yang merupakan keturunan Palembang asli, tetapi memang jarang yang masih mampu menjalankan tradisi itu.Kesenian Dul Muluk, suatu sandiwara panggung yang mengawinkan unsur melayu dengan padang pasir, sudah jarang ditemui. Padahal dulu, kesenian ini begitu digemari karena sarat petuah dan kental komedi. Jika orang ada pesta di rumahnya, entah kawinan atau sunatan, belum lengkap jika tidak mendatangkan kelompok ini. Namun pada perkembangannya, Dul Muluk tergeser oleh hingar bingar diskotik kampung ala organ tunggal dan goyangan biduan orkes melayu. Selama hidupku, aku pernah menyempatkan diri bertemu dengan kelompok Dul Muluk ini. Pada umumnya, kegiatan tersebut hanya menjadi pekerjaan sampingan saja. Karena mereka punya pekerjaan tetap lain yang mampu mempertahankan kepulan asap di dapur. Sulit untuk menggantungkan hidup hanya dengan bermain Dul Muluk.Mungkin cuma kesenian rebana yang masih cukup mencorong sampai saat ini. Hanya saja itu mungkin karena di kota ini kebudayaan Islam masih tetap melekat erat. Jadi, kesenian rebana yang sarat pujian kepada Allah ini tetap dibutuhkan dalam segenap kegiatan ritual adat keagamaan. Hanya saja sekarang peralatannya bukan sekedar alat musik yang dipukul itu saja, sebab gitar elektrik dan organ juga kadang ikut menemani. Lagu-lagunya juga lebih ngepop, mulai menyentuh kegiatan keseharian, pokoknya ala penyanyi kasidah tanah air yang sekarang dapat kita dikenal melalui kaset dan CD.Kalau tempat wisata lain? Apa ya. Aku sendiri paling kenal Pulo Kemaro, Bukit Siguntang dan sungai Musi ini. Padahal sebenarnya, di wilayah ini banyak yang dapat dijadikan daya tarik wisata berlebih. Terutama wisata penelitian dan ilmu pengetahuan. Termasuk urusan menguak misteri tentang Antu Banyu itu. Tetapi anehnya, kenapa tidak ada pihak yang tertarik untuk membuka tabir ini? Apakah karena kisah tentang Antu Banyu ini sebelumnya terlalu banyak diselimuti mitos magis sehingga mengaburkan realita tentang mahluk itu sendiri? Entahlah. Yang jelas, aku dan teman-teman baruku ini bertekad menyelesaikan kasus ini. Apapun terjadi. Doakan kami.... (to be continue)Riwayat Penulis
Nama Lengkap : Sri Widiya Putri Burlian AqiebNama Popular : Widya BurlianLahir : Palembang, 24 Agustus 1978Anak : Rudysta Dihyah Al-KalabiAlumnus Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Jurusan Administrasi Niaga. Sebelum menjadi penulis novel, lebih banyak aktif berkarir di dunia jurnalistik, diantaranya pernah menjadi wartawan di Koran Harian Transparan Palembang, wartawan di Majalah Komoditas Jakarta dan sekarang masih bergabung di MATAPENA SINERGI, perusahaan yang bergerak di bidang media cetak dan elektronik, diantaranya menjadi Konsultan Bulletin Berjangka BAPPEBTI dan pendiri Tabloid Margin dan marginTV.com (pionir media khusus Perdagangan Berjangka).
Related Posts :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)












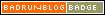



0 komentar: